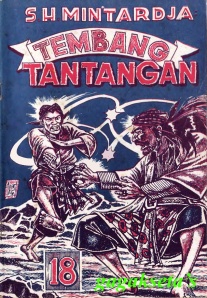 “KAU tahu bahwa barang-barang itu adalah barang-barang berharga?”
“KAU tahu bahwa barang-barang itu adalah barang-barang berharga?”
“Aku tahu, Ki Sanak” jawab orang tua itu.
“Kau tahu dari mana aku mendapatkan barang-barang itu?”
“Aku tahu Ki Sanak”
“Jadi kau tahu bahwa aku seorang perampok yang baru saja merampok rumah orang kaya?”
“Aku tau Ki Sanak”
Tiba-tiba saja Guntur Ketawang itu mencabut kerisnya. Keris yang diambilnya di rumah orang yang kaya raya itu. Dijulurkan-nya keris itu sehingga melekat di dada orang tua yang menolong-nya, “Kalau demikian, maka kau akan dapat melaporkannya kepada orang yang berwenang memerintah disini.
“Ayah“ terdengar suara anak remaja itu.
“Kau pun akan mati anak cengeng” bentak Ki Guntur Ketawang.
Anak itu justru melangkah setapak-setapak mendekati ayahnya yang berdiri bagaikan membeku. Ujung keris Ki Guntur Ketawang masih tetap melekat didadanya.
“Aku akan membunuhmu. Kemudian aku akan pergi meninggalkan rumahmu yang buruk ini”
Laki-laki tua itu sama sekali tidak berbuat apa-apa. Wajahnya pun nampak dingin tanpa gejolak apa pun yang menyiratkan gejolak perasaannya.
“Aku akan membunuhmu, kau dengar“ Ki Guntur Ketawang itu membentak semakin keras.
Tetapi laki-laki itu tetap saja berdiri dengan wajah yang beku pula.
Ki Guntur Ketawang tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia ingin segera pergi. Namun ia tidak mau meninggalkan jejak di rumah itu. Karena itu, maka laki-laki tua itu dan anaknya yang remaja harus mati.
Tanpa belas kasihan, maka Ki Guntur Ketawang itu berusaha menghunjamkan keris itu di dada laki-laki tua yang telah menolongnya.
Tetapi tiba-tiba keris di tangannya itu bagaikan menyala. Nyalanya memancar kebiru-biruan sangat menyilaukan. Bahkan terasa hulu keris itu menjadi sangat panas di tangan Ki Guntur Ketawang, sehingga seakan-akan Ki Guntur Ketawang itu sedang menggenggam bara.
Dengan gerak naluriah, Ki Guntur Ketawang ingin melepaskan keris itu. Tetapi rasa-rasanya telapak tangannya telah melekat pada hulu keris yang sangat panas melampaui panasnya bara batok kelapa.
“Lepaskan, lepaskan” teriak Ki Guntur Ketawang. Tetapi keris itu tidak lepas dari tangannya. Bahkan ketika ia meloncat surut sambil mengibas-kibaskan keris itu, namun keris itu tetap melekat di telapak tangannya. Bahkan Ki Guntur Ketawang itu tidak mampu membuka genggaman tangannya sendiri.
Dalam kebingungan itu, serasa ada getaran panas yang mengalir dari keris itu menyusup ke urat-urat darahnya, mengalir sampai ke jantung.
Ki Guntur Ketawang itu pun seakan-akan telah terpelanting dan jatuh terbaring di pembaringan.
Ki Guntur Ketawang itu menjadi pingsan lagi. Ketika ia sadar, laki-laki tua itu masih menungguinya bersama anaknya yang sudah remaja. Bahkan laki-laki tua itu ialah menitikkan air di mulut Ki Guntur Ketawang itu.
Tubuh Ki Guntur Ketawang terasa sakit dimana-mana. Sendi-sendinya menjadi sangat lemah. Tulang-tulangnya bagaikan tidak berdaya lagi menyangga tubuhnya.
“Ki Sanak” gumam Ki Guntur Ketawang yang masih berbaring di amben bambu yang beralaskan tikar pandan di atas galar bambu wulung, “Kenapa kau biarkan aku hidup? Ketika kau menemukan aku di jurang serta sempat mengumpulkan harta benda yang berharga itu, kenapa kau tidak membiarkan aku mati dan memiliki harta benda berharga itu? Kemudian ketika aku jatuh pingsan di rumah ini, kenapa kau tidak membunuhku, meskipun aku sudah berniat membunuhmu. Jika kau membunuhku, maka harta benda itu pun akan menjadi milikmu”
“Aku tidak berhak mengambil nyawa seseorang, Ki Sanak. Bahkan jika ada kemungkinan, aku justru harus berusaha menolong nyawa seseorang yang berada dalam bahaya, meskipun keputusan akhir ada di tanganNya. Selain itu, harta yang tidak ternilai harganya itu bukan milikku, sehingga aku tidak boleh memilikinya meskipun aku dapat melakukannya”
“Tutup mulutmu, Ki Guntur Ketawang berteriak. Tetapi dadanya menjadi sangat sakit. Bahkan terasa cairan yang hangat mengalir di sela-sela bibirnya”
Ki Guntur Ketawang itu mengeluh tertahan.
”Kenapa Ki Sanak?” bertanya orang tua itu.
”Dadaku sakit sekali. Tulang-tulangku di seluruh tubuhku”
Orang itu pun kemudian telah menuangkan beberapa tetes cairan ke dalam mulut Ki Guntur Ketawang.
Keadaan Ki Guntur Ketawang ternyata menjadi lebih buruk daripada sebelum ia berniat membunuh orang tua itu. Namun sikap orang tua itu tidak berubah. Bersama anak remajanya ia tetap saja dengan sungguh-sungguh merawat Guntur Ketawang.
Ternyata orang tua itu memerlukan waktu beberapa hari untuk merawat Ki Guntur Ketawang sehingga ia mampu bangkit berdiri. Namun keadaan tubuhnya sudah tidak dapat pulih lagi sebagaimana sebelumnya.
Sejak saat itulah, Guntur Ketawang merasa seakan-akan sorot kuasa yang tidak terlawan menembus jantungnya, sehingga setiap kali perasaan Guntur Ketawang telah disisipi oleh perasaan yang sebelumnya tidak pernah dikenalnya dengan sungguh-sungguh selain baru didengarnya seperti dongeng saja.
Dan sejak saat itulah tubuh Ki Guntur Ketawang menjadi cacat.
Semula Ki Guntur Ketawang tidak mau menerima kenyataan itu. Bahkan Ki Guntur Ketawang merasa lebih baik mati saja daripada hidup dengan cacat di tubuhnya. Namun akhirnya Ki Guntur Ketawang merasakan bahwa cacat itulah yang telah melemparkannya kembali ke dunianya yang terang. Cacat itu justru diterimanya dengan rasa terima kasih yang tinggi, karena Yang Maha Agung telah berkenan mengendalikannya, sehingga ia tidak mampu lagi untuk melanglang di daerah pesisir Utara, menakut-nakuti para penghuninya. Menyebar kematian dan bahkan kematian yang sia-sia. Ia bukan lagi menjadi bagaikan burung elang yang buas yang memburu anak ayam yang tidak berdaya..
Akhirnya Ki Guntur Ketawang itu pun merasa bahwa ia telah sembuh meskipun ia tidak dapat melepaskan diri dari kendali cacat tubuhnya itu.
“Aku benar-benar telah sembuh adi. Maksudku bukan sembuh dari cacat di tubuhku. Tetapi aku telah sembuh dari cacat di jiwaku”
Wajah Ki Sangga Geni justru menjadi tegang. Jika benar yang dikatakan oleh kakak seperguruannya itu, maka Ki Sangga Geni merasa bahwa kepergiannya ke pesisir utara dengan menempuh perjalanan yang jauh itu akan sia-sia. Ia sudah bertekad untuk menantang kakak seperguruannya itu untuk berperang tanding. Selain untuk memenuhi janjinya, bahwa ia akan datang menantang kakak seperguruannya itu, maka ia pun ingin menguji kemampuannya setelah ia menempa diri dan menyelesaikan laku sampai tuntas.
Hampir diluar sadarnya, Ki Sangga Geni itu pun berkata, “Kakang, apakah kakang berkata sebenarnya, bahwa kakang telah cacat?”
“Ya, adi. Tubuhku telah cacat bersamaan dengan kesembuhan cacat di jiwaku”
“Tidak. Kakang tentu hanya berpura-pura. Kakang hanya ingin menghindari agar aku tidak dapat memenuhi janjiku untuk menantang kakang berperang tanding. Kakang telah menghinaku dengan tidak mau membunuhku saat kakang telah mengalahkan aku. Waktu itu aku berjanji, bahwa pada suatu saat aku akan datang mencari kakang. Melanjutkan perang tanding itu hingga tuntas”
“Kenapa adi tidak percaya?”
“Aku harus dapat memenuhi pernyataanku pada waktu itu”
Ki Guntur Ketawang itu pun tersenyum. Ia pun kemudian berpaling kepada muridnya sambil berkata, “Sumbaga. Bantulah adikmu Luminta”
Sumbaga mengerti maksud gurunya. Gurunya tentu tidak ingin ia ikut mendengarkan pembicaraan gurunya dengan adik seperguruannya itu.
Karena itu, maka ia pun berkata, “Baik, guru. Aku akan ke belakang”
Tetapi Sumbaga sudah mendengar serba sedikit pernyataan Ki Sangga Geni. Karena itu, maka jantung Sumbaga itu pun telah tergetar.
Karena itu, maka Sumbaga pun justru dengan hati-hati telah mendekati pintu pringgitan dari ruang dalam untuk mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh gurunya serta paman gurunya itu. Gurunya sudah menjadi cacat. Karena itu, maka ia tidak akan dapat membiarkan perlakuan yang tidak adil terhadap gurunya itu meskipun Sumbaga tahu, bahwa ilmu paman gurunya yang disebut murid terbaik itu, tentu sangat tinggi, bahkan mungkin melampaui ilmu gurunya.
Dalam pada itu, di pringgitan, Ki Sangga Geni itu pun berkata, “Kakang jangan menjadi pengecut. Mungkin kakang tahu, bahwa aku telah menyelesaikan laku yang harus aku jalani. Karena itu, maka tiba-tiba saja kakang telah berpura-pura cacat agar kakang tidak usah melakukan perang tanding karena kakang yakin bahwa dalam perang tanding itu kakang akan kalah”
“Aku tahu, adi Sangga Geni. Aku tahu, seandainya aku tidak cacat, aku memang akan kalah. Apalagi setelah aku cacat seperti ini. Aku sama sekali sudah tidak bertenaga. Aku tidak lagi mampu menggerakkan tangan dan kakiku seperti dahulu. Aku sudah kehilangan segala-galanya. Yang ada sekarang dalam diriku adalah pasrah, apa yang akan terjadi pada diriku”
“Bohong. Omong kosong” bentak Ki Sangga Geni. Lalu katanya, “Kakang. Bagaimanapun keadaan kakang, aku akan tetap melakukan sebagaimana yang sudah aku ucapkan. Aku datang untuk menantangmu berperang tanding sampai tuntas. Aku tidak peduli, apakah kau akan melawan atau tidak”
Ki Guntur Ketawang itu pun mengangguk-angguk. Katanya, “Jika demikian, adi. Terserah saja kepadamu. Tetapi sayang, bahwa aku tidak akan mampu melayanimu. Aku tidak lagi menguasai unsur-unsur gerak yang mana pun juga. Tulang-tulangku telah rapuh pula. Karena itu, maka pekerjaanmu akan menjadi sangat mudah meskipun akan sangat mengecewakanmu”
Namun sementara itu, pintu pringgitan pun terbuka. Luminta keluar dari pintu pringgitan dengan ragu-ragu. Ia membawa nampan berisi minuman dan beberapa potong makanan”
Ki Guntur Ketawang tersenyum. Katanya, “Letakkan saja di situ Luminta”
“Baik, guru”
Demikian Luminta meletakkan nampan berisi minuman dan makanan, maka ia pun segera masuk kembali ke pintu pringgitan. Demikian ia menutup pintu pringgitan, maka ia pun justru bergeser ke samping Sumbaga untuk ikut mendengarkan pembicaraan gurunya dengan adik seperguruannya itu.
“Kakang” berkata Ki Sangga Geni kemudian, “Aku tidak mempunyai banyak waktu. Marilah, kita akan menyelesaikan persoalan kita itu dengan cara seorang laki-laki”
“Minumlah dahulu adi. Seorang cantrikku telah membuatkan minuman bagimu”
“Tidak. Aku tidak datang untuk semangkuk minuman dan sepotong makanan. Tetapi aku datang untuk membuat perhitungan”
“Adi” berkata Ki Guntur Ketawang, “bagiku segala sesuatunya telah lewat”
“Tidak. Terbukti kakang masih mempunyai murid yang tentu masih akan melanjutkan tindak kekerasan yang pernah kakang lakukan sebelumnya”
“Tidak, adi. Aku justru minta kepada mereka untuk menebus segala macam kejahatan yang pernah aku lakukan. Aku ajari mereka untuk melakukan kebaikan, membantu mereka yang memerlukan bantuan dalam ujud apa pun menurut kemampuan mereka. Aku berharap agar murid-muridku tidak berbuat sebagaimana aku lakukan”
“Jika kakang benar-benar cacat serta tulang-tulang kakang menjadi rapuh, bagaimana kakang dapat membimbing murid kakang?”
“Bukankah aku masih mempunyai mulut untuk memberikan aba-aba kepada mereka? Aku memang tidak berharap agar mereka menjadi orang yang berilmu sangat tinggi bahkan tidak terbatas. Aku justru berharap agar mereka dapat membantu memberikan penyuluhan tentang garap sawah. Tentang kerajinan tangan dan mengenai berbagai bidang kerja yang lain“
“Cukup, kakang. Sekarang aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Aku telah datang memenuhi janjiku. Aku tidak percaya bahwa kakang sekarang sudah cacat. Kakang tentu hanya ingin agar aku tidak dapat memenuhi janjiku pada waktu itu untuk menantang kakang berperang tanding sampai tuntas”
“Adi. Terserah, apa yang akan kau lakukan. Tetapi aku sekarang benar-benar sudah rapuh. Aku tidak mempunyai kekuatan lagi apalagi ilmu yang tinggi sebagaimana ilmumu. Sedangkan pada saat aku masih menjadi hantu di pesisir Utara aku merasa tidak dapat mengalahkanmu, apalagi sekarang”
“Cukup, cukup. Kakang bersiaplah. Turunlah ke halaman. Melawan atau tidak melawan, aku akan membunuhmu”
“Baiklah adi. Jika itu yang kau kehendaki. Jika kau benar-benar inginkan kematianku, maka aku tidak akan berkeberatan. Mungkin memang sudah menjadi garis hidupku, bahwa aku harus mati di tangan saudara seperguruanku”
Ki Sangga Geni itu pun segera bangkit dan melangkah ke halaman. Sementara itu dengan susah payah, Ki Guntur Ketawang pun telah bangkit pula dan berjalan bertumpu pada tongkatnya turun ke halaman.
Demikianlah beberapa saat kemudian keduanya telah berhadapan di halaman bangunan utama padepokan kecil yang sepi itu.
“Kakang. Bersiaplah. Kau tahu bahwa aku bukan orang yang mempunyai belas kasihan. Kau pernah menyebutku sebagai iblis yang biadab. Aku memang berguru pada iblis yang biadab itu. Karena itu, jangan berharap bahwa aku akan mengasihanimu dengan sikapmu yang pura-pura itu”
“Terserah kepadamu. Apa yang akan kau lakukan, adi”
“Berhentilah berpura-pura. Hadapi aku sebagaimana kau hadapi aku beberapa tahun yang lalu. Kau tentu tidak ingin perang tanding yang akan kita lakukan itu menghapus kebanggaanmu bahwa kau telah mengalahkan aku serta menghinaku dengan tidak membunuhku, karena kau tahu, bahwa sekarang aku sudah menuntaskan laku yang harus aku jalani dan yang belum sempat aku jalani beberapa tahun yang lalu”
“Semuanya sudah lampau bagiku, adi. Tidak ada lagi kebanggaan atas satu kemenangan. Tidak ada pula dendam dan kebencian. Apalagi kepura-puraan. Karena itu, jika kau memang berniat membunuhku, sekarang adalah waktunya. Aku sudah pasrah jika kematian itu memang akan menjemput sekarang dengan perantaraan tanganmu”
“Persetan. Jangan mengiba-iba seperti laki-laki cengeng”
“Tidak. Aku tidak mengiba-iba. Tetapi aku memang tidak dapat berbuat apa-apa”
Ki Sangga Geni termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi ragu-ragu. Nampaknya Ki Guntur Ketawang itu benar-benar pasrah serta tidak ingin melakukan perlawanan sama sekali.
Sementara itu, tiba-tiba saja ketiga muridnya pun telah turun pula ke halaman. Sumbaga yang tertua diantara mereka pun berkata, “Paman. Jika paman ingin membunuh guru, maka selesaikan pula kami bertiga. Kami tahu, bahwa paman adalah seorang berilmu tinggi yang tidak terlawan, apalagi kami adalah para murid yang tidak memusatkan kemampuan kami pada olah kanuragan. Karena itu, kami yang tentu tidak akan berarti apa-apa bagi paman, sudah seharusnya pasrah pula sebagaimana guru menyerahkan segala sesuatunya kepada kemauan paman”
“Gila. Kau ajari murid-muridmu menjadi laki-laki cengeng, kakang”
“Aku ajari mereka untuk melihat kenyataan”
“Tetapi bukan seharusnya seorang laki-laki mati dengan tangan bersilang di dada. Matilah dengan tangan terentang”
“Bagi kami apa pun yang terjadi, tidak ada bedanya, paman. Nah, paman dapat segera menyelesaikan kami berempat dalam sekejap. Kemudian paman dapat meninggalkan padepokan ini dengan jiwa yang sudah terpuaskan karena paman sudah memenuhi janji paman kepada diri sendiri, bahwa paman akan datang kembali untuk membunuh guru dan sebaiknya sekaligus dengan murid-muridnya yang tersisa”
Ki Sangga Geni itu pun berdiri termangu-mangu. Wajahnya menjadi sangat tegang sehingga seakan-akan telah membara.
“Licik. Licik. Dengan cara yang sangat licik dan pengecut kalian membuat aku menjadi sangat kecewa seumur hidupku”
“Tidak paman. Lakukan apa yang ingin paman lakukan”
“Gila. Kalian semua sudah gila. Licik dan pengecut. Buat apa aku membunuh pengecut seperti kalian. Kemenanganku bukan lagi satu kebanggaan”
“Maafkan aku, adi Sangga Geni. Aku memang tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pula murid-muridku. Kami tentu sangat mengecewakanmu”
Gigi Ki Sangga Geni pun gemeretak. Dengan suara yang bergetar ia pun menggeram, “Perjalananku sia-sia. Aku sudah menempuh jarak yang jauh, sehingga aku sampai di pesisir Utara. Tetapi yang aku temui adalah seorang pengecut serta murid-muridnya yang juga pengecut”
Ki Guntur Ketawang tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja Ki Sangga Geni itu pun melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan padepokan kecil yang sepi di Karawelang itu.
Sepeninggal Ki Sangga Geni, Ki Guntur Ketawang pun berkata, “Aku bangga terhadap kalian, bahwa kalian tidak berniat melawan. Sukurlah bahwa kalian tahu benar ajaran-ajaran yang telah aku berikan kepadamu disamping olah kanuragan. Meskipun kalian sudah tuntas menyerap ilmu dari kitab yang aku berikan kepadamu dengan beberapa perbaikan watak dan sifat dari unsur-unsur geraknya disana-sini, sehingga nafas sesat yang terdapat dalam ilmu itu sudah tersingkir, serta dengan sisipan-sisipan dari hasil perenungan kita bersama, dan ajaran agama yang kita anut, namun kalian tidak menjadi kumalungkung serta deksura untuk melawan pamanmu. Aku melihat pamanmu masih berpijak pada ilmu iblisnya”
“Kami berusaha menyesuaikan dengan keadaan guru”
“Tetapi adi Sangga Geni tidak percaya, bahwa aku benar-benar sudah menjadi catat seperti ini. Cacat yang telah melemparkan aku kembali ke kehidupan yang benar menurut ajaran agama”
“Seperti yang guru katakan, bahwa catat badani pada guru itu justru telah menyembuhkan cacat jiwani yang guru sandang sebelumnya”
“Ya. Karena itu, aku berpesan mawanti-wanti kepada kalian, ilmu yang telah kalian kuasai itu jangan justru mendorong kalian untuk menjadi cacat secara jiwani. Aku berhadap bahwa kalian dapat membantu aku, menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Karena secara badani aku sendiri tidak mampu lagi melakukannya, maka aku hanya dapat berharap, bahwa kalianlah yang akan melakukannya”
“Kami akan menjalankan segala perintah guru” jawab ketiganya hampir berbareng.
“Sudahlah. Kita bersukur, bahwa tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan yang kita lakukan dapat memberikan sedikit bahan perenungan bagi adi Sangga Geni”
“Ya, guru. Semoga”
“Sumbaga dan Luminta. Bersiap-siaplah. Pekan mendatang aku minta kalian menelusuri perjalanan pamanmu kembali ke pertapaannya di lambung Gunung Sumbing. Kalian dengan diam-diam harus mencari keterangan serba sedikit tentang pamanmu”
“Baik, guru”
“Usahakan agar tidak terjadi benturan kekerasan dengan pamanmu. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, jika tidak dapat dihindari kalian boleh melindungi diri kalian sendiri. Tetapi kalian masing-masing tentu masih belum dapat menandingi kemampuan pamanmu. Tetapi jika kalian berdua bergabung, maka aku berharap bahwa kalian akan mampu menyelamatkan diri. Jangan segan-segan menghindar dari pertempuran jika itu terjadi diluar kemampuan kalian untuk menghindari”
“Ya, guru”
“Tetapi ingat, kalian tidak boleh menyimpang dari pijakan pegangan hidup kalian”
“Sendika guru”
“Nah, sekarang beristirahatlah. Bawa minuman dan makanan itu ke belakang. Nampaknya pamanmu tidak sempat makan dan minum. Sejak di perjalanan, hatinya tentu sudah dibalut oleh niatnya untuk membalas dendam atas kekalahannya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu aku tidak membunuhnya, karena ia adalah adik seperguruanku. Tetapi justru karena itu, maka ia merasa terhina sehingga ia berniat pada kesempatan lain untuk datang dan menantangku berperang tanding sampai tuntas”
Ketiga orang murid Ki Guntur Ketawang itu pun kemudian pergi ke belakang sambil membawa hidangan yang berada di pringgitan.
Dalam pada itu, dengan kemarahan dan kecewa yang membakar jantungnya, dengan tergesa-gesa Ki Sangga Geni telah meninggalkan padepokan Karawelang yang kecil dan sepi itu. Tetapi didalam padukuhan yang sepi itu ternyata telah menyala api neraka yang panasnya tujuh kali lipat panasnya baja yang membara.
“Bodoh, dungu” geram Ki Sangga Geni, “Kenapa aku juga menjadi cengeng sehingga aku tidak berani membunuh mereka berempat? Kenapa aku justru melarikan diri dari bingkai niat kepergianku ke padepokan di Karawelang itu?”
Ki Sangga Geni menghentakkan kakinya. Tetapi kemudian Ki Sangga Geni berjalan terus.
Ketika senja turun, maka Ki Sangga Geni pun telah berdiri di atas pasir basah di pesisir Utara.
Jantung di dada Ki Sangga Geni rasa-rasanya masih saja membara oleh kemarahan, kekecewaan dan kebenciannya terhadap kakak seperguruannya yang tiba-tiba telah menjadi cengeng dan pengecut. Juga murid-muridnya yang begitu mudahnya siap untuk membunuh diri, mati bersama-sama gurunya yang menurut pengakuannya telah menjadi cacat itu.
“Persetan dengan mereka” geram Ki Sangga Geni kemudian, “Mereka bukan sasaranku yang sebenarnya. Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan mereka. Persoalan yang ada padaku sekarang adalah persoalanku dengan Ki Margawasana. Aku tidak akan peduli lagi dengan orang lain. Yang penting, aku dapat membunuh Ki Margawasana. Waktuku tidak terlalu banyak lagi”
Ki Sangga Geni pun kemudian telah mengambil keputusan untuk kembali ke padepokannya di kaki Gunung Sumbing. Dari padepokannya ia akan langsung pergi ke Gebang untuk menemui Ki Margawasana. Ia akan menantangnya berperang tanding sampai tuntas. Seorang diantara keduanya, apakah dirinya atau Ki Margawasana harus mati”
Dengan demikian, maka Ki Sangga Geni pun segera meninggalkan pesisir Utara, sementara senja pun telah bertukar menjadi malam.
Ki Sangga Seni masih saja berjalan meskipun malam menjadi semakin gelap. Ia baru berhenti setelah kakinya yang terantuk-antuk batu padas yang berujung runcing terasa pedih ketika kakinya itu terperosok ke dalam air yang merembes dari tanggul parit yang bocor sehingga menggenangi jalan.
Ki Sangga Geni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Sangga Geni itu berniat untuk bermalam di banjar padukuhan yang ada dekat dihadapannya.
“Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan tidur di banjar. Itu tentu akan lebih baik dari pada aku harus membakar banjar itu”
Sebenarnyalah ketika Ki Sangga Geni sampai di banjar, maka ia pun telah pergi menemui penunggu banjar.
“Ki Sanak” berkata Sangga Geni, “Aku minta ijin untuk bermalam di banjar ini. Bukankah itu diperkenankan?”
Penunggu banjar yang sedang duduk-duduk bersama isterinya di ruang dalam, segera bangkit berdiri sambil bertanya, “Siapa diluar?”
“Aku Ki Sanak, aku kemalaman di perjalanan, aku ingin minta ijin untuk bermalam di banjar ini”
Penunggu banjar itu pun dengan tergesa-gesa membuka pintu rumahnya. Dilihatnya Ki Sangga Geni berdiri di depan rumahnya.
“Ki Sanak kemalaman di perjalanan?”
“Ya, Karena itu, aku minta ijin untuk bermalam di sini”
Ternyata penunggu banjar itu menerima permintaan itu dengan senang hati. Dengan ramah ia pun menjawab, “Baiklah Ki Sanak. Marilah, aku siapkan sebuah bilik di serambi banjar yang dapat kau pergunakan”
“Terima kasih” sahut Ki Sangga Geni. Tetapi ia tidak begitu senang terhadap keramahan seseorang.
“Biar orang lain menganggapnya seorang yang ramah, yang baik hati dan yang suka menolong. Apa artinya kebaikan yang sekedar untuk mendapat pujian” berkata Ki Sangga Geni didalam hatinya, “Kenapa ia tidak bersikap wajar saja?“
Penunggu banjar itu pun kemudian membuka pintu sebuah bilik di serambi banjar. Menyalakan lampu minyak kelapa yang ada di ajug-ajug. Kemudian membersihkan sebuah amben yang sudah dialasi dengan sebuah tikar pandan yang putih dengan tebah sapu lidi.
“Silahkan Ki Sanak. Tetapi aku tidak dapat menyediakan tempat yang lebih baik dari ini”
“Terima kasih. Ini sudah cukup bagiku. Sebenarnya aku dapat tidur dimana saja. Tetapi karena kebetulan aku berjalan melewati sebuah banjar, maka aku pun singgah untuk bermalam”
“Silahkan beristirahat. Ki Sanak nampak letih”
“Tidak. Aku tidak pernah merasa letih. Jika aku berhenti dan bermalam di banjar ini, karena pada umumnya di malam hari kita sebaiknya tidur. Itu saja”
Penunggu banjar itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian menyahut, “Ya. Sebaiknya kita tidur di malam hari”
Ketika penunggu banjar itu kemudian meninggalkan Ki Sangga Geni di biliknya, maka Ki Sangga Geni pun membaringkan tubuhnya di amben itu. Ia memang tidak merasa letih. Tetapi ia memang ingin berbaring.
Tetapi sejenak kemudian Ki Sangga Geni itu pun bangkit lagi untuk pergi ke pakiwan.
Ketika Ki Sangga Geni itu masuk kembali ke biliknya, maka penunggu banjar itu menyusulnya sambil berkata, “Ki Sanak. Aku silahkan Ki Sanak singgah di rumahku sejenak”
“Ada apa?“ bertanya Ki Sangga Geni. Ia mulai curiga kepada penunggu banjar itu. Tetapi penunggu banjar itu menjawab, “Isteriku telah menyiapkan makan malam bagi Ki Sanak”
“Bagiku?“
“Ya”
“Ki Sanak dan isteri Ki Sanak belum pernah mengenal aku. Kenapa Ki Sanak dan isteri Ki Sanak memerlukan menyibukkan diri untuk menyiapkan makan malamku? Bukankah aku hanya seorang yang menumpang tidur di banjar itu”
“Ya. Tetapi bukankah sudah seharusnya kita saling membantu. Ki Sanak hari ini menempuh perjalanan panjang. Menurut pendapat kami, Ki Sanak tentu letih, lapar dan haus. Maaf jika ternyata dugaan ini keliru. Namun tidak ada salahnya jika kami menyediakan selain tempat untuk beristirahat, juga makan dan minuman hangat. Kami juga melakukannya bagi orang-orang lain yang bermalam di banjar ini”
Ki Sangga Geni mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menolak. Sebenarnyalah bahwa Ki Sangga Geni memang merasa lapar setelah ia mandi dan berbenah diri.
Sejenak kemudian, maka Ki Sangga Geni telah berada di rumah penunggu banjar itu. Rumah yang sederhana dengan perabot yang sederhana pula. Penunggu banjar itu pasti bukan orang yang berkelebihan. Tetapi ia sudah memberikan sebagian dari miliknya yang sedikit itu kepada orang yang bermalam di banjar. Bahkan semua orang yang bermalam di banjar.
“Kenapa ia tidak menghemat saja agar ia dapat menabung dan membeli kambing atau bahkan lembu. Kenapa ia harus membelanjakan uangnya untuk orang-orang yang tidak dikenalnya”
Tetapi Ki Sangga Geni pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Dihadapannya ada nasi hangat serta minuman yang hangat pula.
“Telur itu kami ambil dari petarangan di belakang. Kami mempunyai beberapa ekor ayam yang kebetulan ada di-antaranya yang sedang bertelur” berkata isteri penunggu banjar itu. Lalu katanya, “Sedangkan sayuran itu kami petik dari kebun kami sendiri. Lembayung dan kacang panjang. Demikian pula tuntut pisang keluthuk itu”
Ki Sangga Geni mengangguk-angguk. Makan malam yang disediakan oleh isteri penunggu banjar itu, meskipun sederhana, tetapi rasanya enak sekali. Demikian pula wedang jahe yang bukan saja masih hangat, tetapi juga dapat menghangatkan tubuhnya.
Setelah makan dan minum, maka Ki Sangga Geni pun dipersilahkan untuk kembali ke bilik yang disediakan baginya di serambi belakang banjar.
Malam itu Ki Sangga Geni yang kenyang itu dapat tidur nyenyak. Demikian ia menyelarak pintu dari dalam, serta merenungi sikap penunggu banjar itu, maka Ki Sangga Geni pun telah membaringkan dirinya di pembaringan. Sejenak kemudian, maka ia pun telah tertidur lelap.
Pagi-pagi sekali Ki Sangga Geni telah terbangun. Setelah mandi dan berbenah diri, maka sebelum matahari terbit, Ki Sangga Geni itu pun minta diri untuk melanjutkan perjalanan.
Tetapi ternyata sebelum Ki Sangga Geni berangkat meninggalkan banjar itu, isteri penunggu banjar itu sudah menyediakan minuman hangat serta ketela pohon yang direbusnya pakai legen kelapa.
Ki Sangga Geni termangu-mangu sejenak. Bahkan diluar sadarnya Ki Sangga Geni pun bertanya, “Kenapa kalian bersusah payah menyediakan minuman dan makanan bagiku. Orang yang lewat dan bermalam di banjar ini? Kenapa kalian begitu peduli kepadaku?”
Kedua orang suami isteri penunggu banjar itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian penunggu banjar itu pun berkata, “Ki Sanak. Seperti sudah aku katakan, bahwa kami melakukannya kepada siapa pun yang bermalam di banjar ini. Kami merasa berkewajiban untuk melakukannya sebagai sesama. Kadang-kadang kami membayangkan, betapa letihnya jika kami sendiri yang melakukan perjalanan dan kemalaman sehingga harus menginap di banjar padukuhan. Bukankah kami harus bertenggang-rasa, sehingga kami merasa wajib untuk melakukannya”
Ki Sangga Geni tidak menjawab. Tetapi ada dorongan di-dalam dirinya untuk tidak menolak kebaikan penunggu banjar itu
Ki Sangga Geni pun kemudian duduk sambil menghirup minuman hangat, kemudian makan ketela pohon yang direbus dengan legen kelapa.
Sudah puluhan, bahkan ratusan kali Ki Sangga Geni makan ketela pohon yang direbus dengan legen kelapa. Tetapi pagi itu rasa-rasanya agak lain. Terasa betapa nikmatnya ketela pohon itu, sehingga tanpa disadarinya Ki Sangga Geni telah menghabiskan dua kerat besar ketela pohon rebus itu.
Baru kemudian Ki Sangga Geni itu menyadarinya. Karena itu, maka ia pun berkata, “Maaf Ki Sanak. Ketela pohon rebus Ki Sanak terasa nikmat sekali, sehingga aku hampir menghabiskannya”
“Silahkan Ki Sanak. Silahkan. Masih banyak tersisa di dapur. Bahkan jika selera Ki Sanak sesuai, Ki Sanak dapat membawanya untuk bekal di jalan”
“Tidak. Tidak. Terima kasih”
Sejenak kemudian ketika cahaya matahari mulai membayang di langit, maka Ki Sangga Geni itu pun minta diri. Ada perubahan sikap pada Ki Sangga Geni. Orang yang jarang sekali tersenyum itu, dapat juga tersenyum sambil minta diri.
“Selamat jalan Ki Sanak. Semoga Ki Sanak selamat sampai ke tujuan”
Ki Sangga Geni pun kemudian meninggalkan banjar itu. Ketika ia melewati gerbang padukuhan, maka dihadapannya terbentang sawah yang luas. Padi yang mulai bergerak disentuh angin pagi yang lembut.
Ki Sangga Geni masih terkesan sikap penunggu banjar itu. Ia belum pernah mengenal dirinya. Tetapi tanggapannya begitu baik kepadanya. Bahkan isterinya pun telah menjadi sibuk untuk menyediakan makan malamnya serta minuman dan makanan menjelang keberangkatannya pagi ini.
Namun kemudian ia pun menggeram, “Hanya orang-orang dungu yang hatinya lemah berbuat demikian. Mereka berbuat baik untuk mendapat pujian serta usaha mereka untuk menyelamatkan diri. Kalau orang lain menganggapnya orang baik, maka mereka tidak akan diganggu orang”
Ki Sangga Geni itu pun kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan mengibaskan kesannya terhadap suami isteri penunggu banjar itu. Tetapi ternyata kesan itu masih saja selalu melekat di kepalanya. Bahkan bukan saja sikap ramah dan kepedulian penunggu banjar itu. Tetapi juga sikap beberapa orang lain yang pernah ditemuinya di perjalanan.
Ternyata masih banyak, bahkan justru pada umumnya orang-orang yang dijumpainya bersikap baik.
Ki Sangga Geni itu menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun mempercepat langkahnya agar ia dapat segera sampai ke sebuah padepokan kecil di kaki Gunung Sumbing. Ki Sangga Geni berniat untuk tidak bermalam lagi di perjalanannya meskipun ia akan berjalan sampai tengah malam.
Ki Sangga Geni yang tubuh dan jiwanya telah ditempa oleh laku yang berat itu memang tidak merasa letih di perjalanannya yang panjang. Karena itu, maka Ki Sangga Geni jarang sekali berhenti untuk beristirahat. Hanya ketika terik matahari terasa membakar tubuhnya, sekali-sekali Ki Sangga Geni berhenti ditempat yang teduh oleh bayangan pepohonan di pinggir jalan. Tetapi hanya sebentar. Ki Sangga Geni pun segera berjalan pula.
Tidak seperti saat ia berangkat, maka diperjalanan pulang, Ki Sangga Geni tidak lagi tertarik untuk membunuh. Bahkan Ki Sangga Geni agaknya tidak sempat lagi menguji tingkat ilmunya dengan mencari lawan yang namanya mencuat di daerah yang dilewatinya. Segenap perhatiannya telah dipusatkannya kepada Ki Margawasana. Ia telah berjanji untuk datang kepadanya setahun setelah kekalahannya dari Ki Margawasana.
Ternyata Ki Sangga Geni memang kemalaman di perjalanannya seperti yang telah diduganya. Jalan yang dilaluinya kadang-kadang tidak terlalu bersahabat. Jalan-jalan sempit berbatu-batu padas serta lorong-lorong yang licin di jalan yang menelusuri tebing, justru menghambatnya.
Tetapi Ki Sangga Geni memang tidak berniat untuk berhenti. Meskipun malam turun, namun Ki Sangga Geni masih juga berjalan terus.
Demikian besar kemauannya untuk segera sampai di. padepokannya, maka Ki Sangga Geni itu pun berjalan terus sampai menjelang tengah malam.
Kedatangan Ki Sangga Geni memang mengejutkan beberapa orang yang menunggui padepokannya. Seperti Ki Guntur Ketawang maka Ki Sangga Geni pun hanya mempunyai beberapa orang murid saja di padepokannya yang berada di kaki Gunung Sumbing tidak jauh dari sebuah goa tempatnya bertapa serta tempatnya menerima sorot kegelapan dari dunia yang kelam.
Malam itu, setelah beristirahat sebentar, kemudian mandi dan berbenah diri, maka Ki Sangga Geni pun langsung pergi ke goanya yang telah ditinggalkannya untuk beberapa hari.
Di depan patung wajah iblisnya, Ki Sangga Geni itu pun bersujud sambil berkata, “Iblis Yang Mulya. Tolong hambamu ini. Kuatkan kepercayaan dan keyakinanku akan ajaran-ajaranmu. Beberapa orang yang sangat aku benci telah mengguncang keyakinanku. Mereka berusaha mempengaruhi aku dengan perbuatan-perbuatan baiknya yang dengan sengaja dilakukan di depanku. Perbuatan yang tidak kau sukai ya Iblis yang Mulya”
Ki Sangga Geni itu pun memandang patung wajah iblisnya dengan gejolak didalam dadanya.
Tiba-tiba saja mata wajah iblis itu pun mulai menjadi merah membara. Terdengar gaung yang menggetarkan ruangan didalam goa itu seakan-akan goa itu telah diguncang oleh gempa.
“Kepadamu akan mengabdi Iblis Yang Mulya. Berilah kekuatan jiwani agar aku tidak goyah dari keyakinanku akan ajaran-ajaranmu semua”
Getar didalam goa itu menjadi semakin keras. Gaung yang terdengar didalam goa itu pun seakan-akan menjadi semakin keras pula.
Baru beberapa saat kemudian, semuanya mereda. Akhirnya segala sesuatunya menjadi tenang kembali. Mata patung wajah iblis itu pun menjadi semakin pudar pula sehingga akhirnya padam sama sekali.
“Terima kasih Iblis yang Mulya. Aku akan melupakan semua kebaikan itu. Kebaikan orang-orang cengeng itu kepadaku, serta kebaikan yang pernah aku lakukan dengan tidak sengaja”
Ki Sangga Geni itu pun membungkuk hormat sampai dahinya menyentuh lantai goa itu sambil berkata, “Tuntun hambamu ini menemui Ki Margawasana. Beri hambamu kekuatan untuk dapat membunuhnya”
Ki Sangga Geni pun kemudian keluar dari goa itu dan kembali ke padepokan kecilnya.
Murid-muridnya kemudian telah melayaninya. Ada yang mempersiapkan minuman. Ada yang mempersiapkan makanan serta yang lain mempersiapkan makan bagi Ki Sangga Geni yang baru saja datang itu.
Terdengar di kandang seekor ayam berkaok-kaok. Namun suaranya pun segera lenyap di telan sepinya malam.
Beberapa saat kemudian, seorang cantrik telah menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan yang ada. Jadah ketan ireng serta jenang nangka yang dibuat oleh seorang cantrik karena nangkanya yang masak di halaman belakang padepokan itu jatuh sendiri dari pohonnya karena sudah terlalu matang.
“Nasi serta lauknya sedang dipersiapkan guru” berkata cantrik itu.
“Ya. Aku menunggu”
Di dapur dua orang cantrik yang memang terbiasa masak, sedang sibuk mempersiapkan makan bagi Ki Sangga Geni. Ketika nasi masak, maka lauk serta sayurnya pun telah masak pula. Seekor ayam telah disembelih. Dua ekor gurameh yang besar, yang diambil langsung dari belumbang di kebun belakang padepokan kecil itu.
Demikian nasi serta lauknya masak, maka dua orang cantrik pun segera menghidangkannya.
Selera Ki Sangga Geni memang sesuai dengan masakan kedua orang cantriknya itu. Karena itu, ketika tercium bau lauk pauk yang disiapkan oleh kedua orang cantrik itu, Ki sangga Geni pun justru merasa semakin lapar.
Tetapi ketika Ki Sangga Geni itu makan, maka rasa-rasanya nasi serta lauk pauknya itu tidak senikmat yang di suguhkan semalam oleh penunggu banjar itu. Meskipun masakannya jauh lebih sederhana, tetapi ketika ia makan, rasa-rasanya ia tengah berada dalam satu bujana andrawina di satu perhelatan yang mewah.
Tetapi malam itu ia tidak begitu dapat menikmati masakan kedua orang cantriknya yang biasanya dianggapnya mampu menyediakan makanan terbaik baginya.
Namun kemudian Ki Sangga Geni itu pun menggeram, “Tidak. Aku tidak mau dipengaruhi oleh kebaikannya sehingga keyakinan serta kepercayaan kepada diriku menjadi goyah”
Dengan menuntaskan ilmunya serta menjalani laku terakhir dari kitab yang dimilikinya, maka Ki Sangga Geni harus benar-benar tenggelam dalam ajaran-ajaran dalam keyakinan dan kepercayaannya. Bahwa akhirnya, kuasa di bumi serta di dunia abadi akan berada di tangan Iblis Yang Mulya. Segala macam kuasa kebaikan akan musna dan kehilangan pengikutnya, karena ternyata kuasa kebaikan itu tidak menjanjikan apa-apa kecuali mimpi-mimpi yang akhirnya akan lenyap dihembus oleh kenyataan yang justru baka.
Demikianlah, maka Ki Sangga Geni itu pun berniat untuk beristirahat satu dua hari di padepokannya. Kemudian ia pun akan segera menempuh perjalanan ke Gebang. Perjalanan ke Gebang memang tidak sejauh perjalanan ke pesisir Utara. Tetapi ia sengaja akan datang sedikit lebih awal dari yang dijanjikan. Jika ia berangkat dua hari lagi, maka masih ada waktu tersisa menjelang waktu yang setahun dijanjikannya itu.
“Jika Ki Margawasana juga mengasah ilmunya, aku akan sempat melihat, apa saja yang dilakukannya” berkata Ki Sangga Geni didalam hatinya, “Mudah-mudahan Ki Margawasana itu belum selesai. Ia memperhitungkan masih ada waktu sekitar sebulan lagi”
Demikianlah, Ki Sangga Geni pun berada di padepokannya untuk beristirahat selama dua hari. Dalam dua hari itu, ia sempat menilik tingkat kemampuan murid-muridnya yang hanya beberapa orang saja itu”
“Lusa aku akan pergi lagi” berkata Ki Sangga Geni, “Aku akan memenuhi janjiku untuk membuat perhitungan dengan Ki Margawasana. Meskipun aku masih mempunyai waktu sebulan kurang sedikit, tetapi aku sengaja datang lebih awal. Jika saja persiapan Ki Margawasana masih belum selesai, aku akan dapat melihat, apa saja yang dipersiapkan menjelang kematiannya”
“Apakah ada diantara kami yang akan ikut bersama guru?”
Ki Sangga Geni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, “Dua orang diantara kalian akan ikut bersamaku. Tetapi kalian tidak akan mencampuri urusanku dengan Ki Margawasana. Kalian hanya akan menjadi saksi, apa yang akan terjadi. Kalian akan menjadi saksi, bahwa aliran perguruan kita akan dapat mengalahkan seorang yang dibangga-banggakan oleh mereka yang menyebut dirinya menganut aliran putih. Selanjutnya, kalian akan menjadi saksi, bahwa mereka yang menyebut aliran putih itu semakin lama akan semakin terkikis habis sehingga akhirnya, aliran hitam lah yang akan menguasai bumi ini”
Murid-muridnya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi Ki Sangga Geni masih belum menunjuk, siapakah yang dimaksud dengan kedua orang yang akan ikut bersamanya itu.
“Dengarlah. Pengaruh Iblis yang Mulya tidak akan dapat terhapus dari muka bumi ini. Justru sebaliknya, mereka yang mengaku pengikut aliran putih, akan dimusnahkan. Kebohongan, dendam dan dengki serta segala jenis kejahatan tidak akan dapat dihapuskan sepanjang masa. Jika kemudian nampak warna-warna putih, itu hanya sekedar kulitnya saja. Tetapi isinya tentu pancaran aliran hitam”
Murid-muridnya masih mengangguk-angguk. Namun Ki Sangga Geni pun kemudian berkata, “Sekarang beristirahatlah. Besok aku akan menunjuk dua orang diantara kalian”
Murid-muridnya pun segera meninggalkan Ki Sangga Geni yang kemudian duduk sendiri. Ia masih berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan terbaik menghadapi tantangan kehidupan.
Jika sekilas-sekilas masih terbayang kelakuan baik dari beberapa orang, maka Ki Sangga Geni pun segera mengusirnya dari relung-relung di hatinya.
Bahkan ia pun mencoba untuk memaksa dirinya menyesali pesan-pesannya yang diucapkan dihadapan orang-orang yang merasa ditolongnya dari penindasan Ki Pentog di Ngadireja. Bahkan Ki Sangga Geni pun mulai mentertawakan dirinya sendiri karena ia telah berharap agar murid-murid Kiai Pentog itu kembali ke jalan yang benar.
“Jalan yang benar yang mana?” Ki Sangga Geni itu tiba-tiba saja menggeram.
Demikianlah, maka di hari berikutnya, Ki Sangga Geni telah bersiap-siap untuk berangkat. Ia telah menunjuk dua orang diantara murid-muridnya yang hanya sedikit itu untuk pergi bersamanya ke Gebang, menemui Ki Margawasana yang akan ditantangnya berperang tanding sampai tuntas.
“Jika Ki Margawasana juga berpura-pura cacat seperti kakang Guntur Ketawang, atau alasan-alasan apa saja, maka aku tidak akan membiarkannya hidup. Aku tidak peduli. Ki Margawasana harus mati”
Dengan demikian, maka Ki Sangga Geni telah memantapkan niatnya. Membunuh Ki Margawasana.
Di hari berikutnya, di saat matahari terbit. Ki Sangga Geni bersama dua orang muridnya telah siap untuk berangkat ke Gebang.
Kepada murid-muridnya yang ditinggalkannya, Ki Sangga Geni telah memberikan beberapa pesan untuk menjaga padepokan mereka dengan baik.
Perjalanan ke Gebang memang tidak begitu panjang. Jika tidak” ada hambatan di perjalanan, maka Ki Sangga Geni akan sampai di Gebang pada saat malam turun menjelang wayah sepi bocah. Bahkan lebih cepat lagi.
Pada saat matahari mulai merayap naik, Ki Sangga Geni serta dua orang muridnya itu pun meninggalkan regol padepokan kecilnya yang berada dekat sebuah goa yang dipergunakan oleh Ki Sangga Geni untuk bertapa.
Ternyata mereka bertiga tidak mengalami hambatan yang berarti diperjalanan. Ketika terjadi salah paham di sebuah kedai, maka murid-murid Ki Sangga Geni telah dapat mengatasinya, sehingga Ki Sangga Geni sendiri tidak perlu untuk ikut turun tangan.
Dua orang yang merasa dirinya tidak terkalahkan, dengan wajah tengadah memasuki sebuah kedai sementara Ki Sangga Geni dan kedua muridnya sedang berada di kedai itu. Ketika pelayan kedai itu menghidangkan pesanan Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya, kedua orang itu telah membentak-bentak dengan kasar.
“Seharusnya kalian melayani kami lebih dahulu” teriak seorang diantara mereka, sehingga orang-orang lain yang berada di kedai itu menjadi ketakutan.
“Tetapi, tetapi Ki Sanak itu bertiga telah datang lebih dahulu, serta sudah memesan minuman dan makanan sejak tadi”
Yang seorang lagi tiba-tiba saja telah bangkit. Ditendangnya minuman dan makanan yang akan dihidangkan itu sehingga tumpah berhamburan di lantai. Bahkan minuman yang tumpah itu telah membasahi baju salah seorang murid Ki Sangga Geni.
“Kau basahi bajuku” bentak murid Ki Sangga Geni.
“Persetan kau. Kau tidak tahu siapa kami?”
Murid Ki Sangga Geni itu tidak menjawab. Tetapi tangannya langsung menampar mulut orang itu sehingga orang itu terdorong beberapa langkah surut.
“Setan kau” geram yang seorang. Sementara itu orang yang telah ditampar mulutnya itu pun telah meloncat menyerang dengan kakinya. Tetapi sikap kedua orang itu telah menjadi bencana bagi diri mereka sendiri.
Dalam sekejap seorang diantara mereka berteriak. Kakinya telah dipatahkan oleh murid Ki Sangga Geni, sementara yang lain pun menjadi kesakitan pula. Tangannya yang dipilin itu pun telah menjadi retak pula.
Keduanya pun kemudian terkapar di lantai kedai itu. Murid-murid Ki Sangga Geni itu masih juga merusak susunan syaraf keduanya sehingga keduanya akan menjadi cacat sepanjang umur mereka. Keduanya tidak akan dapat lagi menyombongkan diri karena kemampuan mereka.
Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya pun segera meninggalkan kedai itu sebelum sempat makan dan minum.
Pemilik kedai itu tidak berani bertanya apa pun kepada Ki Sangga Geni serta kedua orang muridnya. Namun seorang murid Ki Sangga Geni itu pun berkata, “Jika kedua orang itu sering membuat onar disini, ia tidak akan lagi dapat berbuat apa-apa untuk selanjutnya. Keduanya akan menjadi cacat di sisa hidupnya.
Pemilik kedai serta orang-orang yang ada didalam kedai itu termangu-mangu. Jika yang dikatakan itu benar, maka mereka akan merasa berterima kasih. Terutama pemilik kedai itu. Kedua orang itu setiap kali telah datang ke kedai itu dengan sikap yang sangat kasar, sementara pemilik kedai serta orang-orang yang menyaksikannya tidak ada yang berani mencegahnya.
Namun kedua orang itu telah terkapar di lantai di dalam kedai itu.
Pemilik kedai itu pun kemudian telah menghubungi Ki Bekel untuk memberikan laporan tentang kedua orang itu, “Apa yang terjadi?”
Pemilik kedai itu menceriterakan apa yang telah terjadi dengan kedua orang itu dengan kesaksian orang-orang yang melihatnya.
Ki Bekel pun kemudian telah memberitahukan keadaan kedua orang itu kepada keluarga mereka, yang kemudian telah mengambil mereka untuk dibawa pulang.
Seorang tabib yang diminta untuk mengobati mereka mengatakan, bahwa sulit untuk dapat memulihkannya kembali.
Tetapi orang-orang disekitarnya justru berharap, agar keduanya tidak akan dapat menjadi pulih kembali.
Sementara itu Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya telah melanjutkan perjalanan. Mereka pun kemudian singgah di kedai berikutnya. Ternyata di kedai itu mereka tidak menjumpai persoalan yang dapat membuat mereka harus bertindak.
Perjalanan mereka selanjutnya tidak menjumpai hambatan sama sekali. Karena itulah, maka mereka sampai di Gebang lebih cepat dari dugaan mereka.
Keduanya sampai di Gebang pada saat matahari tenggelam di balik bukit. Senja yang kemerah-merahan bagaikan telah membakar langit.
Tetapi Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya tidak dapat menjumpai Ki Margawasana di Gebang, karena Ki Margawasana sedang berada di bukit kecilnya.
Dengan mendapat ancar-ancar dari orang tua yang menunggu rumah Ki Margawasana di Gebang, maka Ki Sangga Geni pun langsung naik ke bukit kecil itu. Sehingga sedikit di lewat senja, mereka telah sampai di gubug kecil Ki Margawasana yang berada di atas bukit kecil itu.
“Bukan main” berkata Ki Sangga Geni, “satu tempat yang sangat menarik. Sayang, kita sampai disini setelah lewat senja, sehingga kita tidak dapat melihat betapa menyenangkannya tempat ini”
“Besok kita akan dapat melihatnya, guru?”
“Ya. Besok kita akan dapat melihatnya”
Dalam pada itu, Ki Margawasana yang sedang menyalakan beberapa lampu minyak kelapa di gubug kecilnya terkejut melihat kedatangan Ki Sangga Geni bersama dua orang muridnya. Dengan ramah Ki Margawasana pun mempersilahkan Ki Sangga Geni serta kedua orang muridnya itu masuk ke ruang dalam.
Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya pun kemudian masuk kedalam rumah kecil itu dan duduk di ruang dalam di temui oleh Ki Margawasana.
“Kalian dalam keadaan baik-baik saja Ki Sangga Geni?” bertanya Ki Margawasana.
“Kami baik-baik saja. Mungkin Ki Margawasana belum mengenal kedua orang ini. Keduanya adalah muridku. Tetapi jangan cemas, bahwa aku akan melibatkan mereka dalam persoalan diantara kita. Aku membawa mereka sekedar untuk menjadi saksi atas kematangan ilmu gurunya. Mereka harus yakin, bahwa ilmu gurunya adalah ilmu terbaik di muka bumi ini”
Ki Margawasana mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya, “Apa yang akan mereka saksikan?”
“Bukankah aku berjanji untuk datang kepadamu setahun lagi sejak kita bertarung di padepokan yang pernah kau pimpin dan yang sekarang dipimpin oleh muridmu itu”
“Apakah kau masih selalu mengingatnya?”
“Tentu Ki Margawasana”
“Kenapa kau tidak dapat melupakannya?”
“Aku bukan pengecut. Aku tentu akan datang memenuhi janjiku. Bahkan aku datang sedikit lebih awal. Waktunya masih sekitar sebulan kurang sedikit”
“Sudah cukup lama Ki Sangga Geni. Sudah waktunya untuk dilupakan”
“Tidak. Bahkan seandainya waktunya dua tahun, lima tahun atau sepuluh tahun sekalipun”
Ki Margawasana menarik nafas panjang. Sementara Ki Sangga Geni pun berkata, “Tetapi aku tidak akan mempercepat waktu sebagaimana aku janjikan. Jika kau masih belum selesai dengan persiapan-persiapanmu, lanjutkan saja sampai waktunya datang. Kita akan berperang tanding sampai tuntas”
Ki Margawasana menarik nafas panjang.
“Ki Margawasana” berkata Ki Sangga Geni kemudian, “Kau jangan mencari-cari alasan untuk membatalkan perang tanding ini. Apa pun yang akan terjadi, maka aku akan tetap menantangmu perang tanding sampai tuntas”
Ki Margawasana mengangguk-angguk. Katanya, “Kalau itu keputusanmu yang tidak dapat ditawar lagi, maka aku pun tidak akan dapat ingkar”
“Baik. Tetapi aku tetap berperang pada waktu yang kita sepakati. Kita akan berperang tanding sebulan lagi. Sambil menunggu, aku akan tetap berada di sini. Sementara itu, Ki Margawasana dapat meneruskan persiapan Ki Margawasana menghadapi perang tanding itu”
“Apa yang harus aku persiapkan?”
“Mungkin Ki Margawasana masih harus menyempurnakan beberapa unsur gerak yang kurang mapan. Mungkin Ki Margawasana masih harus menjalani laku untuk mempersiapkan unsur-unsur gerak yang akan dapat Ki Margawasana andalkan”
“Aku sudah lama siap, Ki Sangga Geni. Aku pun telah siap pula dengan andalanku, karena aku Kuasa di atas segala Kuasa”
Ki Sangga Geni tertawa. Katanya, “Beberapa kali akan menjumpai orang yang berkata seperti yang kau katakan itu. Tetapi aku selalu dapat membunuhnya. Ternyata kekuasaan Tuhan hanyalah sekedar khayalan, kekuasaan Tuhan akan berakhir kecewa. Bahkan jika keyakinan itu ditrapkan untuk melawanku, maka ia akan menjadi lumat seperti debu. Beberapa orang pernah aku bantai tanpa sempat mengaduh. Kekuasaan Tuhan itu ternyata membiarkannya tersayat-sayat oleh kekuatanku”
“Kau pun tentu mempunyai andalan. Aku tahu, bahwa kau menggantungkan kekuatanmu itu kepada Iblis”
“Ya. Aku adalah hamba terkasih dari Iblis Yang Mulya itu. Iblis yang Mulya itu akan mematahkan Kekuasaan Tuhan, dan menjadikannya budaknya”
“Kau bermimpi buruk, Ki Sangga Geni”
“Aku memang sering bermimpi buruk. Tetapi untunglah aku selalu mampu menghindari bujukan-bujukan untuk menggoyah-kan keyakinanku”
“Kau pernah merasa terbujuk karenanya?”
“Ya. Tetapi keyakinanku teguh”
“Jika demikian, kau pernah mendapatkan peringatan langsung ke pusat jantungmu. Sayang, bahwa kau telah menyia-nyiakannya”
“Peringatan apa yang kau maksud? Ki Margawasana. Aku memang harus mengibaskan godaan-godaan yang berusaha menggoyahkan keyakinanku itu. Agaknya kau juga akan berusaha berbuat demikian itu. Tetapi jangan berharap bahwa keyakinanku itu dapat goyah”
Ki Margawasana menarik nafas panjang. Ia tidak dapat mengerti, kenapa sikap seseorang menghadapi pergulatan antara baik dan buruk dapat terbalik sama sekali. Tetapi nampaknya Ki Sangga Geni bahkan berusaha untuk tetap berpegang kepada keyakinannya yang sesat itu.
“Keyakinannya itu akan terhapus bersamaan dengan akhir dari hayatnya” berkata Ki Margawasana di dalam hatinya.
Namun dalam pada itu, maka Ki Margawasana pun berkata, “Kita akan berbicara lagi nanti. Sekarang aku akan pergi ke dapur. Aku sendiri disini Ki Sangga Geni. Karena itu, maka aku harus merebus air dan membuat minuman sendiri. Aku harus menanak nasi serta membuat lauknya untuk menjamu Ki Sangga Geni serta murid-muridnya”
“Kau akan menyiapkan hidangan buat kami?“
“Ya, Ki Sangga Geni”
“Murid-muridku semuanya pandai masak. Sayang aku tidak mengajak dua orang muridku yang terbaik. Meskipun demikian, murid-muridku ini akan dapat membantumu”
“Aku sudah terbiasa melakukannya sendiri”
“Tetapi hanya untuk kau minum dan kau makan sendiri. Sekarang kami ada disini, sehingga harus disiapkan minuman dan makanan lebih banyak. Karena itu, biarlah kedua orang muridku ini membantumu”
“Baiklah, “Lalu katanya kepada kedua murid Ki Sangga Geni marilah. Kita akan pergi ke dapur”
Dibantu oleh kedua orang murid Ki Sangga Geni, maka Ki Margawasana pun telah menyiapkan minuman dan makan bagi tamu-tamunya. Ki Margawasana sempat memetik kacang panjang serta daun ketela pohon yang masih muda. Sambal terasi dan telur dadar.
Setelah makan malam, maka Ki Margawasana pun mempersilahkan ketiga orang tamunya beristirahat.
Ketiganya pun kemudian masuk ke dalam bilik yang disediakan bagi, mereka bertiga. Satu-satunya bilik yang ada di rumah kecil itu.
“Kau akan tidur dimana Ki Margawasana?“ bertanya Ki Sangga Geni.
“Bukankah ada amben yang lebih besar dari pembaringan di bilik itu di ruang depan” sahut Ki Margawasana.
Ki Sangga Geni tertawa.
Namun ternyata Ki Sangga Geni dan kedua orang cantriknya tidak segera tidur. Mereka mendengar derit pintu terbuka. Agaknya Ki Margawasana telah keluar lewat pintu butulan.
Kepada murid-muridnya Ki Sangga Geni berkata, “Lihat, apa yang akan dikerjakan oleh Margawasana. Mungkin ia sedang berlatih untuk meningkatkan ilmunya. Selain sanggarnya, Ki Margawasana mempunyai banyak tempat untuk berlatih disini. Satu sanggar terbuka yang sangat luas”
Dengan hati-hati kedua orang muridnya itu pun telah keluar pula dari biliknya. Mereka berniat untuk mengikuti Ki Margawasana yang keluar dari dalam rumahnya lewat pintu butulan. Tetapi mereka keluar lewat pintu dapur yang menghadap ke pakiwan yang berada disebelah sumur.
Kedua orang itu telah mengenali pintu itu karena mereka mendapat kesempatan untuk membantu Ki Margawasana menyiapkan hidangan makan malam bagi Ki Sangga Geni serta dua orang muridnya.
Demikian mereka berada di luar, maka mereka pun dengan sangat berhati-hati bergeser ke arah pintu butulan. Tetapi mereka sudah tidak melihat bayangan Ki Margawasana.
Dalam kegelapan mereka beringsut terus. Mereka menduga, bahwa Ki Margawasana telah pergi ke sebuah padang rumput yang agak luas, yang agaknya juga merupakan sanggar terbuka bagi Ki Margawasana. Di padang rumput itu terdapat berbagai macam alat untuk melakukan latihan-latihan agar tubuh Ki Margawasana tetap tegar di hari-hari tuanya.
Namun kedua orang itu tidak menyadari, justru Ki Margawasana lah yang telah mengawasi mereka berdua.
Meskipun demikian, ketika mereka mendekati padang rumput itu, mereka memang melihat Ki Margawasana berdiri di pinggir sambil berpegangan pada sepotong bambu.
Seorang dari kedua orang murid Ki Sangga Geni itu menggamit kawannya sambil memberi isyarat tentang keberadaan Ki Margawasana di pinggir padang rumput itu.
Kawannya mengangguk. Ia pun telah melihat orang tua itu pula.
Tetapi ternyata Ki Margawasana tidak berlatih dengan sepotong bambu itu. Ia pun tidak melakukan apa-apa di padang rumput itu. Tetapi Ki Margawasana itu pun kemudian beringsut meninggalkan tempatnya.
Kedua orang itu berusaha untuk dapat mengikuti, kemana Ki Margawasana itu pergi.
Ternyata Ki Margawasana itu pergi ke tepi belumbangnya. Terdengar beberapa kali kelepak ikan-ikan yang berada di dalam belumbang itu.
“Apa yang akan dilakukannya” desis seorang diantara kedua orang murid Ki Margawasana itu.
Yang lain menggeleng sambil memberikan isyarat agar kawannya itu diam.
Mereka melihat Ki Margawasana itu duduk di sebuah batu yang besar di pinggir belumbang. Tetapi Ki Margawasana tidak berbuat apa-apa.
Kedua orang itu hanya dapat menunggu.
Angin malam diatas bukit kecil itu semakin lama terasa semakin dingin. Di kejauhan terdengar suara burung malam menyentuh sepinya malam.
Tetapi ternyata bahwa Ki Margawasana tidak berbuat apa-apa. Ia duduk-duduk saja diatas batu besar itu sambil memandangi belumbang yang airnya memantulkan keredip bintang yang berhamburan di langit.
Kedua orang murid Ki Sangga Geni itu menunggui Ki Margawasana beberapa lama. Tetapi karena Ki Margawasana tidak berbuat apa-apa, maka keduanya pun segera kembali ke rumah kecil diatas bukit itu.
Dengan hati-hati pula keduanya masuk lewat pintu dapur.
Namun menurut pendapat mereka, Ki Margawasana masih duduk diatas sebuah batu besar di tepi belumbang.
Namun ketika mereka memasuki ruang dalam, mereka terkejut. Ki Margawasana yang tidur di amben besar yang berada di ruang depan itu pun bangkit sambil menggeliat. Ketika ia melihat kedua orang yang berjalan dengan berjingkat itu, Ki Margawasana sambil menggeliat bertanya, “Darimana Ki Sanak?“
Keduanya memang menjadi bingung sejenak. Namun yang seorang segera mendapatkan jawabnya, “Dari pakiwan Ki Margawasana”
“O“ Ki Margawasana itu mengusap matanya. Namun kemudian ia pun membaringkan dirinya lagi di pembaringan.
Kedua orang murid Ki Sangga Geni itu pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Ki Sangga Geni sendiri ternyata masih juga belum tidur. Ia duduk di atas pembaringannya sambil bersandar dinding.
Seorang dari kedua orang muridnya ia akan berbicara ketika Ki Sangga Geni memberi isyarat agar ia tidak berkata apa-apa. Bahkan Ki Sangga Geni pun memberikan isyarat agar kedua muridnya itu pun berbaring di amben yang agak besar yang dialasi dengan galar serta tikar pandan yang putih. Amben yang cukup besar bagi tidur mereka bertiga.
Kedua orang murid Ki Margawasana itu tidak berkata apa-apa. Dengan isyarat Ki Sangga Geni pun minta agar seorang diantara mereka tidur yang seorang berjaga-jaga.
Keduanya memang terbiasa tidur bergantian. Karena itu, maka mereka pun mengerti apa yang dimaksud oleh Ki Sangga Geni.
Menjelang fajar, Ki Margawasana pun telah terbangun. Ia pun kemudian pergi ke dapur untuk merebus air.
Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya telah terbangun pula. Ketika Ki Margawasana telah pergi ke dapur, maka kedua orang muridnya itu bergantian melaporkan apa yang telah terjadi malam tadi.
“Margawasana dengan sengaja memamerkan kemampuannya kepada kalian” berkata Ki Sangga Geni.
Namun Ki Sangga Geni pun kemudian telah memerintahkan kedua orang muridnya itu untuk pergi ke dapur membantu Ki Margawasana merebus air untuk membuat minuman bagi tamu-tamunya serta bagi Ki Margawasana sendiri.
Hari itu, Ki Sangga Geni bersama kedua orang muridnya telah minta ijin kepada Ki Margawasana untuk melihat-lihat keadaan bukit kecil yang ternyata sangat menarik perhatian mereka. Udara di bukit kecil itu terasa sejuk dan segar. Pepohonan yang seakan-akan memayungi bukit kecil itu, bergoyang ditiup angin lembut.
“Setelah aku membunuh Margawasana” berkata Ki Sangga Geni, “Aku akan menetap di tempat ini”
Kedua orang muridnya termangu-mangu. Seorang di-antara mereka berkata, “Tetapi apakah ahli waris Ki Margawasana akan mengijinkan guru tinggal disini? Bukankah di kaki Gunung Sumbing udaranya juga sejuk? Mungkin kita belum sempat menata padepokan kita sebagaimana tempat tinggal di Margawasana ini. Tetapi jika kita mengaturnya, maka tempat itu tentu juga akan menarik seperti tempat ini”
“Lalu bagaimana dengan goa tempat guru bertapa itu?“ bertanya yang seorang lagi.
Ki Sangga Geni itu pun menarik nafas panjang. Katanya, “Ya. Aku tidak dapat meninggalkan goa itu”
“Yang dapat kita lakukan, guru. Kita akan membuat padepokan kita sesejuk dan sesegar tempat ini. Bukankah pada dasarnya udara di padepokan kita juga sudah sejuk dan segar”
Ki Sangga Geni mengangguk-angguk.
Namun dalam pada itu, selagi mereka berjalan-jalan menyusup dibawah pepohonan di bukit kecil itu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa. Hanya perlahan-lahan. Namun kemudian semakin lama menjadi semakin keras. Bahkan suara tertawa itu bagaikan bergulung-gulung memenuhi bukit kecil itu. Bahkan bukit kecil itu rasa-rasanya telah terguncang, sedangkan semua pepohonan pun telah bergoyang. Daun-daun yang menguning telah runtuh berguguran.
Ki Sangga Geni termangu-mangu sejenak. Sementara kedua orang muridnya sedang berusaha untuk meningkatkan daya tahan mereka agar suara tertawa itu tidak merontokkan isi dada mereka.
“Siapakah yang telah mengganggu ketenangan ini” geram Ki Sangga Geni. Namun Ki Sangga Geni pun yakin, bahwa suara tertawa itu bukan suara tertawa Ki Margawasana. Orang itu tidak akan melakukan perbuatan sekasar itu”
Dalam pada itu, tiba-tiba Ki Sangga Geni pun berteriak pula sekeras suara tertawa itu, “He, siapa kau? Keluarlah. Kita akan berhadapan dengan dada tengadah”
Suara tertawa itu masih saja terdengar di seputar bukit itu. Suara itu seakan-akan berputaran dari segala arah.
“He, jangan bersembunyi” teriak Ki Sangga Geni. Suaranya tidak kalah lantangnya. Justru karena itu, maka bukit kecil itu menjadi semakin terguncang-guncang.
Sementara itu, selagi bukit itu berguncang serta pepohonan bergoyang, seseorang seakan-akan terbang disela-sela pepohonan itu mendekati Ki Sangga Geni. Dalam sekejap prang itu telah berdiri di dekat Ki Sangga Geni.
“Ki Margawasana” desis Ki Sangga Geni.
“Ya. Siapakah yang telah mengganggu ketenangan bukit kecilku ini?“ bertanya Ki Margawasana.
Ternyata orang yang tertawa berkepanjangan sehingga getarnya menggoyahkan bukit itu memang bukan Ki Margawasana.
Suara tertawa itu masih saja terdengar. Disela-sela suara tertawa itu terdengar orang itu berkata, “Bagus. Tenyata Ki Sangga Geni tidak sendiri. Permainan kita nanti tentu akan semakin menarik”
“Keluarlah dari persembunyianmu” berkata Ki Margawasana dengan lantang.
Tetapi suara itu tetap saja melingkar-lingkar di seputar bukit kecil itu.
Akhirnya Ki Margawasana tidak sabar lagi. Dengan gerak tangannya yang berputar, tiba-tiba saja angin pun telah berputar pula disekitarnya. Semakin lama semakin cepat dan semakin melebar, sehingga akhirnya seluruh hutan kecil diatas bukit kecil itu bagaikan telah disergap oleh angin pusaran yang semakin cepat. Pepohonan yang bergoyang oleh getar suara tertawa itu, terayun dengan kerasnya ditiup oleh prahara yang deras.
Pepohonan yang bagaikan diguncang itu berayun semakin lama semakin keras.
Akhirnya sesosok tubuh telah meluncur dan hingga di tanah dengan lunaknya.
“Bukan main” berkata orang itu. Ia sudah tidak tertawa lagi, meskipun ia masih saja tersenyum-senyum, “Ki Margawasana telah menggoyahkan bukit ini dan menghadirkan prahara yang sangat besar, sehingga aku tidak dapat bertahan di dahan pepohonan di bukit kecilnya ini”
“Hanya kebetulan saja Ki Sanak. Tetapi Ki Sanak ini siapa dan apakah ada keperluan Ki Sanak datang ke bukit kecil ini dengan cara yang sangat mengejutkan itu. Hampir saja bukit kecilku ini runtuh, serta pepohonan yang ada diatasnya roboh silang-melintang”
“Itu berlebihan Ki Margawasana” sahut orang itu. Namun dalam pada itu, Ki Sangga Geni pun berdesis, “Kau. Bukankah kita pernah bertemu?”
“Ya. Kita pernah bertemu. Sekarang pun aku datang untuk menemuimu yang kebetulan kau berada di bukit kecil Ki Margawasana yang sejuk ini”
Ki Margawasana termangu-mangu sejenak. Dengan nada datar ia pun bertanya, “Darimana Ki Sanak tahu namaku? Darimana pula Ki Sanak mengetahui tempat tinggalku ini?”
“Hampir semua orang di dunia olah kanuragan mengenal Ki Margawasana. Jadi jangan heran jika aku juga mengenal Ki Margawasana”
“Ki Sanak” berkata Ki Sangga Geni, “siapakah yang Ki Sanak cari sekarang ini? Aku atau Ki Margawasana?”
“Sebenarnya aku mencari Ki Sangga Geni. Aku mempunyai sedikit kepentingan”
“Jika demikian, marilah aku persilahkan Ki Sanak singgah di rumahku. Apapun keperluan Ki Sanak, kita dapat membicarakannya dengan lebih tenang, “Ki Margawasana mempersilahkan.
“Tidak perlu, Ki Margawasana. Aku tidak akan terlalu lama. Aku hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan persoalanku dengan Ki Sangga Geni”
“Ada apa sebenarnya Ki Sanak?” bertanya Ki Sangga Geni.
“Ki Sangga Geni sudah tahu, bahwa aku adalah saudara sepupu orang yang bernama Pentog di Ngadireja. Beberapa saat setelah Ki Sangga Geni membunuh Pentog, maka aku mencoba menelusuri perjalanan Ki Sangga Geni. Ternyata Ki Sangga Geni pergi ke padepokan di Karawelang. Ki Sangga Geni berniat menemui Ki Naga Wereng yang sebenarnya bernama Ki Rubaya yang kemudian bergelar Ki Guntur Ketawang”
“Ya”
“Tetapi Ki Naga Geni gagal membalas dendam terhadap saudara tua seperguruannya itu. Karena itu, maka Ki Sangga Geni telah menempuh perjalanan kembali ke Gunung Sumbing. Terakhir Ki Sangga Geni telah pergi ke Gebang untuk menemui Ki Margawasana. Ternyata aku berhasil menemui Ki Sangga Geni disini”
“Kita sekarang telah bertemu Ki Sanak. Lalu apa maksud Ki Sanak sebenarnya?”
“Ki Sangga Geni. Aku adalah saudara sepupu orang yang menyebut dirinya Kiai Pentog. Sebenarnyalah bahwa selain saudara sepupu aku juga guru orang yang menyebut dirinya Kiai Pentog itu”
Jantung Ki Sangga Geni berdesir. Dengan ragu-ragu ia bertanya, “Lalu apa maksud Ki Sanak menyusul aku kemari?”
“Sudah aku katakan, bahwa Pentog adalah orang yang telah melakukan banyak kejahatan. Aku yang gurunya merasa tidak mampu lagi untuk mencegahnya. Sehingga pada suatu saat, Ki Sangga Geni telah datang untuk membunuhnya” orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, “Pentog memang tidak pantas untuk diberi ruang gerak, ia harus dihentikan. Namun pada saat aku berusaha menghentikannya, maka Ki Sangga Geni telah datang untuk membunuhnya”
Pada saat matahari mulai merayap naik, Ki Sangga Geni serta dua orang muridnya itu pun meninggalkan regol padepokan kecilnya yang berada dekat sebuah goa yang dipergunakan oleh Ki Sangga Geni untuk bertapa.
“Bukankah kau melihat sendiri, bagaimana aku membunuh Kiai Pentog. Kau sendiri mengatakan bahwa kau menghormati perang tanding yang aku lakukan melawan Kiai Pentog, sehingga kematian Kiai Pentog tidak dapat dibebankan tanggung-jawabnya kepadaku. Jika dalam perang tanding itu aku tidak membunuh, maka tentu akulah yang akan dibunuhnya”
“Aku mengerti. Aku tidak akan mengungkit apa pun juga mengenai perang tanding itu”
“Jadi apakah yang kau kehendaki sekarang?“
“Aku datang untuk menantangmu berperang tanding. Bukan karena kematian Pentog. Tetapi semata-mata karena aku tidak mau disaingi. Aku adalah orang yang memiliki ilmu yang tidak terkalahkan. Kematian Pentog memberikan kesan, terutama kepada orang Ngadireja dan sekitarnya, bahwa kaulah yang terkuat di bumi ini”
Wajah Ki Sangga Geni menjadi tegang. Dengan geram ia pun bertanya, “Jadi, apa maumu sekarang?“
“Kita akan pergi ke Ngadireja, Ki Sangga Geni. Kita akan berperang tanding dihadapan rakyat Ngadireja. Jika aku dapat membunuhmu, maka orang-orang Ngadireja dan sekitarnya, kemudian berita itu akan menjalar pula kemana-mana,. bahwa orang yang membunuh Kiai Pentog telah dibunuh oleh Kiai Surya Wisesa”
“Jadi namamu Surya Wisesa?“
“Ya. Akulah Kiai Surya Wisesa. Orang terkuat dimuka bumi”
“Tetapi kenapa baru sekarang kau datang kepadaku. Bukankah kau menyaksikan kematian muridmu itu?”
“Aku tidak dapat menantangmu waktu itu. Kau sudah terluka di dalam. Dengan memijit hidungmu pun kau tentu sudah akan mati. Karena itu, aku biarkan kau menyembuhkan dirimu sendiri. Baru aku mencarimu dan menantangmu untuk berperang tanding. Jika aku membunuhmu waktu itu, maka aku tidak akan dianggap orang terkuat diatas bumi kita ini. Tetapi orang-orang justru akan menyebutku sebagai seorang pengecut yang licik”
“Bagus Surya Wisesa. Aku juga mempunyai keinginan seperti yang kau inginkan. Aku harus menjadi orang terkuat di bumi kita ini. Aku terima tantanganmu”
“Besok aku tunggu kau di Ngadireja. Malam ini kau dapat menempuh perjalanan ke Ngadireja, sehingga menjelang tengah hari lusa kau sudah berada di arena perang tanding. Aku memilih arena itu tepat diatas arena di saat kau membunuh Pentog”
“Kenapa besok lusa. Kedatanganku disini bukannya sekedar bertamasya. Aku juga mempunyai keperluan yang sangat penting disini”
“Itu bukan urusanku. Jika besok lusa kau tidak berada di arena, maka akulah orang yang tidak terkalahkan itu. Aku akan berteriak kepada setiap orang di Ngadireja yang kemudian tentu akan tersebar, bahwa kau tidak berani menerima tantanganku. Ternyata kau hanyalah seorang pengecut yang sombong”
“Gila kau Surya Wisesa. Baik. Aku terima tantanganmu. Besok lusa aku akan berada di arena perang tanding itu.
Ki Margawasana termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Sangga Geni pun berkata kepada Ki Margawasana, “Waktu kita masih panjang. Aku akan menyelesaikan orang ini lebih dahulu. Baru kemudian kita akan membicarakan persoalan kita”
Ki Margawasana tidak menjawab. Sementara itu Kiai Surya Wisesa itu pun tertawa sambil berkata, “Bagus. Ternyata kau cukup jantan Ki Sangga Geni. Tetapi aku akan membuktikannya apakah besok kau sudah berada di Ngadireja dan esok lusa kau sudah siap untuk berperang tanding”
“Aku akan datang Kiai Surya Wisesa. Kau akan menyesali kesombonganmu. Kau akan mengalami nasib yang sama dengan muridmu. Mungkin kau dapat bertahan lebih lama dari Pentog. Tetapi tidak akan lebih dari sepenginang”
“Aku dapat mengukur diri Ki Sangga Geni. Aku sudah melihat seberapa jauh tataran ilmumu. Karena itu, aku tahu pasti, bahwa kau akan terbunuh di arena perang tanding itu”
“Kita akan melihat, siapakah yang terakhir akan menengadahkan wajahnya. Kau sekarang dapat tertawa. Tetapi lusa kau tidak akan sempat mengaduh lagi”
“Baik. Baik. Sekarang aku akan pergi. Beristirahatlah barang sejenak. Tetapi nanti kau harus berangkat ke Ngadireja agar kau mendapat kesempatan untuk beristirahat sebelum perang tanding itu diselenggarakan”
Ki Sangga Geni tidak menjawab. Namun kemudian ia pun berkata kepada Ki Margawasana, “Nanti aku terpaksa meninggalkan Ki Margawasana”
“Sebelum Ki Margawasana menjawab, maka Kiai Surya Wisesa pun berkata, “Aku minta diri. Waktuku tidak banyak. Aku juga ingin segera berada di Ngadireja untuk beristirahat sebelum aku memasuki perang tanding”
Sejenak kemudian, maka orang yang rambutnya sudah ubanan dan menyebut dirinya Kiai Surya Wisesa itu pun meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan kata-kata apa pun lagi.
Sepeninggal Kiai Surya Wisesa, Ki Sangga Geni pun berkata, “Ki Margawasana. Aku terpaksa pergi lebih dahulu. Persiapkan dirimu baik-baik. Aku akan datang pada saatnya. Aku akan menyelesaikan persoalan kita. Kita tidak dapat hidup serta menghirup udara dari bumi dan langit yang sama”
Ki Margawasana menarik nafas panjang. Katanya, “Ki Sangga Geni. Kenapa bumi kita ini selalu ditaburi oleh dendam dan kebencian. Dimana-mana ditemui benturan kekerasan karena dendam dan nafsu untuk memanjakan diri sendiri”
“Aku bukan orang cengeng seperti kau, Ki Margawasana. Aku terbiasa menyelesaikan persoalan antara laki-laki dengan cara laki-laki. Darah adalah yang terbaik untuk mencuci persoalan antara laki-laki sampai tuntas”
Ki Margawasana menarik nafas panjang.
“Nah, Ki Margawasana. Ijinkan aku beristirahat di rumahmu beberapa saat. Barangkali kau masih dapat menyuguhi aku minum dan makan sekali sebelum aku berangkat ke Ngadireja”
“Tentu Ki Sangga Geni. Aku akan menyiapkan minum dan makan bagi kalian sebelum kalian berangkat ke Ngadireja”
Di rumah kecil Ki Margawasana di atas bukit itu, Ki Margawasana dibantu oleh kedua orang murid Ki Sangga Geni telah mempersiapkan minuman hangat serta makan. Nasi yang mengepul, tiga ekor gurameh bakar yang baunya menggelitik sehingga perut Ki Sangga Geni semakin terasa lapar. Sayur keroto beserta daunnya yang masih muda serta sambel terasi.
“Silahkan Ki Sangga Geni, “Ki Margawasana mempersilahkan Ki Sangga Geni serta kedua orang muridnya untuk makan.
“Murid-muridmu ternyata terampil pula menyiapkan minum dan makan” berkata Ki Margawasana.
“Keduanya bukan yang terbaik untuk bekerja di dapur” sahut Ki Sangga Geni.
“Ki Margawasana tidak makan?” bertanya salah seorang murid Ki Sangga Geni.
“Silahkan. Aku nanti saja. Bukankah aku tidak akan pergi ke mana-mana”
Sementara itu sambil makan, Ki Sangga Geni telah menceritakan serba sedikit tentang orang yang bernama Kiai Pentog. Seorang yang disebut sebagai anak genderuwo dari Gunung Prau. Tetapi ternyata bukan.
“Orang yang berambut ubanan itu tadi mengaku sebagai sepupunya dan ternyata juga sebagai gurunya. Di Ngadireja ia nampak manis dan sama sekali tidak menyesali kematian Kiai Pentog. Tetapi ternyata ia telah mencari dan menyusulku sampai kemari”
“Yang bergejolak di jantungnya bukannya dendam. Tetapi nafsu untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang tidak terkalahkan” berkata Ki Margawasana.
“Itu yang terucapkan dari mulutnya. Tetapi aku yakin, bahwa tentu ada unsur dendam itu pula di hatinya”
“Ki Sangga Geni harus berhati-hati”
“Kau mau mengguruiku? Kau kira kau pantas menasehatiku?”
“Tidak, Ki Sangga Geni. Aku tidak akan menasehatimu. Mungkin kaulah yang lebih pantas mengguruiku. Tetapi aku hanya ingin memperingatkanmu. Bukankah mungkin saja kau melupakan sesuatu?”
“Apa yang mungkin aku lupakan?”
“Bahkan orang itu sempat menyaksikan kau bertarung melawan Kiai Pentog. Selama ini ia telah mempelajarinya serta mencari kelemahan-kelemahan pada ilmumu”
“Tidak ada lagi kelemahan yang dapat diketemukan”
“Tentu ada kelemahannya. Ilmu seseorang tidak akan mungkin sempurna. Nah, dengan mengenali kelemahanmu serta usahanya untuk mencari unsur-unsur yang akan dapat menembus kelemahanmu itu, maka ia akan tampil di arena perang tanding. Sementara itu kau belum dapat mempelajari kelemahan-kelemahannya”
“Aku tidak mencemaskannya. Ilmuku sempurna. Aku telah menerima pernyataan dari Iblis Yang Mulia bahwa isi kitabnya telah aku serap sampai tuntas”
Ki Margawasana menarik nafas panjang.
Sementara itu, Ki Sangga Geni dan kedua muridnya pun telah selesai makan. Sambil bangkit dari tempat duduknya, Ki Sangga Geni itu pun berkata, “Aku akan beristirahat di kebunmu sebentar Ki Margawasana. Nanti, setelah nasi di perutku ini turun, aku akan berangkat”
“Silahkan. Kau tidak tergesa-gesa. Kau masih mempunyai waktu cukup sampai esok lusa”
Ki Sangga Geni itu pun kemudian bersama kedua orang muridnya, duduk beristirahat di bawah pepohonan yang sejuk.
“Kalian ikut ke Ngadireja. Kalian akan menjadi saksi, bahwa tidak ada orang yang dapat mengalahkan aku. Demikian pula orang yang mengaku bernama Kiai Surya Wisesa itu. Besok lusa aku akan melumatkannya. Meskipun ia mengaku guru Kiai Pentog yang tentu saja ilmunya lebih tinggi, tetapi aku masih tetap berada di atas batas tertinggi dari ilmu di perguruan mana pun juga”
“Ya, guru” jawab kedua orang muridnya hampir berbareng.
Sementara itu, di rumah kecilnya, sambil mencuci mangkuk-mangkuk yang kotor, Ki Margawasana sempat merenungi orang yang berambut ubanan. Penglihatan batinnya, mengatakan kepadanya, bahwa orang itu memang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka sebenarnyalah Ki Margawasana agak meragu-kan kemampuan Ki Sangga Geni.
“Namun ilmu Ki Sangga Geni itu pun sudah tuntas pula” desis Ki Margawasana.
Dalam pada itu, setelah beristirahat beberapa lama, maka Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya itu pun telah menemui Ki Margawasana untuk minta diri.
“Selamat jalan Ki Margawasana. Mudah-mudahan Ki Sangga Geni berhasil”
“Aku tentu berhasil. Setelah aku menyelesaikan orang yang menyebut dirinya Kiai Surya Wisesa itu, aku akan segera kembali. Tentu sebelum lewat dari hari yang aku janjikan”
“Aku akan menunggumu, Ki Sangga Geni”
“Aku tentu akan kembali”
Demikianlah, maka Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya itu pun telah meninggalkan bukit kecil itu. Mereka yang datang lebih awal itu ternyata masih harus meninggalkan bukit itu lagi karena tantangan berperang tanding dari orang yang menyebut dirinya Kiai Surya Wisesa.
Sepeninggal Ki Sangga Geni, maka setelah membenahi dirinya, maka Ki Margawasana telah pergi ke sanggarnya yang terbuka. Di tengah-tengah tanah berumput yang agak lapang, Ki Margawasana itu pun duduk sambil memusatkan nalar budinya. Dengan kesungguhan hatinya Ki Margawasana berharap bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan Sumber Keberadaannya, serta arah perjalanan hidupnya. Ki Margawasana berharap, bahwa apa yang dilakukannya tidak menyimpang dari jalan kebenaran sejauh jangkauan nalar budinya, karena Ki Marga-wasana pun menyadari, betapa jauhnya jarak kebenaran sejati dari gapaian nalar budinya yang terlalu pendek itu.
Sementara itu, Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya telah menempuh perjalanan yang jauh. Mereka harus pergi ke Ngadireja untuk menanggapi tantangan perang tanding dari orang yang menyebut dirinya Kiai Surya Wisesa itu.
Namun Ki Sangga Geni yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik, yang sebenarnya dilakukan untuk melawan Ki Margawasana sebagaimana dijanjikannya hampir setahun yang lalu, dapat diandalkannya.
Karena itu, maka Ki Sangga Geni itu sama sekali tidak. merasa cemas, bahwa ia harus berhadapan dengan orang yang menyebut dirinya Kiai Surya Wisesa itu.
Ki Sangga Geni sama sekali tidak menghiraukan apa pun yang ditemui di perjalanannya. Ia ingin segera sampai di Ngadireja. Beristirahat sendiri, kemudian turun ke dalam pertarungan melawan Kiai Surya Wisesa.
Ternyata orang-orang Ngadireja telah mendengar bahwa orang yang telah membunuh Kiai Pentog itu telah ditantang dalam perang tanding oleh saudara sepupu Kiai Pentog. Bukan karena dendam, tetapi mereka akan memperebutkan gelar sebagai seorang terkuat dari dunia olah kanuragan.
Orang-orang Ngadireja dan sekitarnya itu pun menjadi tegang. Bagi mereka, Ki Sangga Geni adalah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dari keganasan Kiai Pentog” Karena itu, mereka berharap, bahwa Ki Sangga Geni akan dapat memenangkan [perang tanding itu.
Namun Kiai Surya Wisesa itu telah menyatakan pula kepada orang-orang di Ngadireja, bahwa ia tidak akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh Kiai Pentog. Ia datang di Ngadireja dengan niat untuk mencegah perbuatan Kiai Pentog. Namun orang lain telah mendahuluinya dan bahkan telah membunuh Kiai Pentog.
“Aku akan melindungi orang-orang Ngadireja” berkata Kiai Surya Wisesa kepada orang-orang Ngadireja, “Jika aku menantang Ki Sangga Geni, bukan karena aku mendendam atas kematian Pentog. Tetapi aku hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang Ngadireja, orang-orang disekitarnya, bahkan orang-orang di seluruh Mataram bahwa aku adalah orang yang memiliki kemampuan serta ilmu tertinggi”
Orang-orang Ngadireja tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mereka sudah terlanjur menganggap Ki Sangga Geni sebagai pahlawan mereka.
Ketika Ki Sangga Geni sampai di Ngadireja, maka ia pun langsung menuju ke banjar kademangan. Orang-orang Ngadireja serta para bebahu menyambutnya dengan penuh harapan, bahwa Ki Sangga Geni akan memenangkan perang tanding itu.
Hari yang menegangkan itu pun akhirnya datang juga. Saat perang tanding antara Kiai Surya Wisesa melawan Ki Sangga Geni.
Sebelum tengah hari, Ki Sangga Geni telah berada di arena perang tanding yang dipilih sendiri oleh Kiai Surya Wisesa.
Sejenak Ki Sangga Geni menunggu. Sementara itu, arena itu telah dilingkari oleh orang-orang Ngadireja yang ingin menyaksikan perang tanding itu. Tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka mengerumuni arena itu dari jarak yang agak jauh.
Baru sejenak kemudian, ketika matahari semakin dekat dengan puncaknya, Kiai Surya Wisesa telah memasuki arena perang tanding itu pula.
“Ternyata kau juga berani datang Ki Sangga Geni”
“Jika kau tidak datang ke arena, maka aku akan memburumu sampai ke ujung bumi sekalipun” sahut Ki Sangga Geni.
“Bagus” jawab Kiai Surya Wisesa“ kita akan segera mulai. Bukankah kau datang bersama muridmu? Mereka akan dapat menjadi saksi. Siapakah diantara kita orang terkuat di muka bumi ini”
“Apakah kau juga membawa saksi?“ bertanya Ki Sangga Geni.
“Rakyat Ngadireja lah yang akan menjadi saksiku”
“Kau ternyata seorang yang sombong sekali Kiai Surya Wisesa. Ketika kita berjumpa beberapa saat lalu, pada saat kematian Kiai Pentog, kau nampak seperti seorang yang rendah hati”
Kiai Surya Wisesa itu pun tertawa. Katanya, “Pada dasarnya aku memang seorang yang rendah hati. Tetapi berhadapan dengan orang seperti kau, Ki Sangga Geni, bukan sepatutnya aku bersikap rendah hati”
“Baik, baik. Sekarang aku sudah ada disini. Aku pun sudah siap untuk melakukan perang tanding untuk menguji, siapakah diantara kita orang terbaik itu”
Kiai Surya Wisesa pun telah mempersiapkan diri pula. Sambil merendahkan dirinya pada lututnya serta satu kakinya ditariknya setengah langkah kebelakang, ia pun berkata, “Kita akan mulai sekarang, Ki Sangga Geni”
Ki Sangga Geni pun segera memiringkan tubuhnya. Ia pun sedikit merendah pula. Kedua tangannya diangkatnya di depan dadanya dengan telapak tangannya yang terbuka serta jari-jarinya yang rapat.
Ketika kemudian Kiai Surya Wisesa meloncat menyerangnya, maka Ki Sangga Geni itu pun bergeser menghindarinya. Namun dengan demikian, maka pertarungan itu pun sudah dimulai. Ki Sangga Geni pun kemudian berloncatan menyerang dengan kaki dan tangannya. Sementara itu Kiai Surya Wisesa pun mengimbanginya dengan serangan-serangan pula.
Demikianlah, maka sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka bergerak semakin lama semakin cepat. Sambar menyambar seperti dua ekor burung elang yang berlaga di udara.
Namun keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi sehingga sulit bagi mereka masing-masing untuk menembus pertahanan lawan. Jika sekali-sekali terjadi benturan, maka keduanya saling bergetar surut satu dua langkah.
Pertarungan itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mereka bertempur semakin keras, sehingga benturan-benturan diantara mereka rasa-rasanya bagai menggoyang pepohonan disekitar arena pertempuran itu.
Orang-orang yang mengitari arena pertarungan itu di tempat yang agak jauh, menjadi sangat berdebar-debar. Sekali-sekali Ki Sangga Geni terdorong surut beberapa langkah. Namun di kesempatan lain, Kiai Surya Wisesa lah yang terdesak surut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka tidak dapat menduga, siapakah diantara keduanya yang akan dapat memenangkan pertempuran itu. Agaknya keduanya mempunyai kemungkinan yang sama.
Ki Sangga Geni yang bertempur dengan semakin meningkat-kan ilmunya, sekali-sekali memang berhasil menyusupkan serangannya disela-sela pertahanan Kiai Surya Wisesa. Ketika tangan Ki Sangga Geni dengan telapak tangan terbuka berhasil menghentak dada Kiai Surya Wisesa, maka Kiai Surya Wisesa itu pun tergetar surut beberapa langkah. Terasa dadanya menjadi panas, serta nafasnya menjadi sesak. Namun dalam waktu singkat Kiai Surya Wisesa berhasil memperbaiki keadaannya. Ketika kemudian Ki Sangga Geni itu meloncat sambil memutar tubuhnya dengan kaki terayun kearah kening, Kiai Surya Wisesa dengan cepat membungkukkan badannya sehingga kaki Ki Sangga Geni itu tidak menyentuhnya. Sementara itu Kiai Surya Wisesa yang merendah justru menjatuhkan dirinya dan menyapu kaki Ki Sangga Geni.
Ki Sangga Geni lah yang justru terbanting jatuh. Namun ketika Kiai Surya Wisesa meloncat bangkit berdiri, Ki Sangga Geni pun telah bangkit berdiri pula.
Namun agaknya Kiai Surya Wisesa berhasil bergerak lebih cepat. Dengan loncatan panjang, kakinya terjulur menyamping. Sementara itu dengan tergesa-gesa Ki Sangga Geni menyilangkan tangannya didadanya.
Benturan itu telah membuat keduanya tergetar selangkah i mundur. Namun sekejap kemudian, keduanya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan.
Ketika keduanya meningkatkan ilmu mereka lebih tinggi lagi, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serangan demi serangan saling susul menyusul. Benturan-benturan pun terjadi semakin sering pula. Sekali-sekali Kiai Surya Wisesa tergetar surut. Di kesempatan lain, Ki Sangga Geni lah yang harus berloncatan surut.
Karena itulah maka mereka pun telah semakin meningkatkan ilmunya. Bahkan keduanya pun telah mengetrapkan berbagai macam ilmu yang semakin tinggi.
Dengan mengetrapkan ilmu meringankan tubuh, maka keduanya itu pun sekali-sekali bagaikan terbang dan bertempur di udara. Bergantian mereka terlempar jatuh. Tetapi dengan cepat mereka pun segera bangkit kembali.
Orang-orang yang menyaksikan pertarungan yang dahsyat itu menjadi semakin berdebar-debar. Keduanya sama sekali tidak mempergunakan senjata. Tetapi arena pertempuran itu bagaikan telah diterpa oleh angin prahara.
Pepohonan yang ada di sekitarnya telah bergoyang. Daun-daun pun berguguran karena ranting-rantingnya yang berpatah-an. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin ngeri. Rasa-rasanya mereka melihat pergulatan antara angin prahara di musim kasanga yang berbenturan dengan badai di hujan angin pada penghujung musim kemarau.
Namun agaknya kedua-duanya masih saja mampu bertahan.
Ki Sangga Geni yang merasa sudah menuntaskan ilmunya dihadapan pepundennya merasa yakin bahwa tidak ada ilmu yang dapat melampaui ilmunya. Seperti yang dikatakannya kepada Ki Margawasana, bahwa ilmuku adalah ilmu yang sempurna.
Sementara itu, Kiai Surya Wisesa, guru orang yang menamakan dirinya Kiai Pentog yang disebut sebagai anak genderuwo dari Gunung Prau itu ternyata juga memiliki ilmu iblis yang dahsyat. Apalagi Kiai Surya Wisesa telah mempelajari dengan saksama kelemahan-kelemahan ilmu Ki Sangga Geni pada saat Ki Sangga Geni bertempur dan bahkan membunuh muridnya, Kiai Pentog.
Karena itu, maka akhirnya, dalam pergulatan yang dahsyat, sebagaimana benturan angin prahara dengan badai menjelang musim kemarau sehingga seakan-akan telah menumbuhkan cleret tahun yang kehitaman itu, Ki Sangga Geni mulai terdesak. Serangan-serangan Kiai Surya Wisesa yang telah mempelajari kelemahan-kelemahan Ki Sangga Geni semakin sering menyusup diantara pertahanan Ki Sangga Geni.
Namun dengan tenaga serta kemampuannya yang sangat besar, serta tatanan geraknya yang semakin keras dan kasar, maka Ki Sangga Geni masih tetap bertahan.
Akhirnya, keduanya sampai pada satu kesimpulan, bahwa mereka tidak akan dapat segera menyelesaikan pertempuran itu, tanpa mempergunakan ilmu pamungkas mereka.
Demikianlah, ketika keduanya bagaikan dua ekor burung yang bertempur di udara itu masing-masing terlempar surut beberapa langkah, mereka seakan-akan menemukan waktu luang untuk melepaskan ilmu pamungkas mereka.
Dalam sekejap keduanya mengambil ancang-ancang. Kemudian hampir bersamaan pula keduanya telah menghentak melontarkan puncak kemampuan mereka yang jarang sekali mereka lepaskan.
Benturan yang dahsyat telah terjadi. Benturan dua ilmu yang sangat tinggi, yang seakan-akan meluncur dari tangan masing-masing.
Rasa-rasanya guntur telah meledak diantara kedua orang itu. Getarannya telah mengguncang udara disekitarnya, sehingga orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu dari tempat yang agak jauh merasakan, betapa getaran itu telah menghentak dada mereka.
Kedua orang yang sedang bertempur itu terlempar beberapa langkah surut. Mereka terbanting dan jatuh terlentang. Getar kekuatan ilmu mereka ternyata telah melukai bagian dalam tubuh mereka masing-masing.
Namun agaknya kekuatan ilmu Kiai Surya Wisesa masih lebih kuat selapis dari kekuatan ilmu Ki Sangga Geni yang merasa bahwa ilmunya sempurna, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang mampu mengatasinya.
Karena itulah, maka Ki Sangga Geni yang memiliki kemampuan serta daya tahan tubuh yang sangat tinggi, telah terbaring diam. Dari sela-sela bibirnya mengalir darah yang merah segar.
Sementara itu, dengan susah payah, Kiai Surya Wisesa pun berusaha untuk bangkit berdiri. Dari mulutnya pun telah meleleh pula darah oleh luka di bagian dalam tubuhnya. Namun Kiai Surya Wisesa masih sempat berdiri. Kemudian berjalan tertatih-tatih mendekati tubuh Ki Sangga Geni.
Dengan tangannya yang gemetar Kiai Surya Wisesa menarik keris yang diselipkannya di punggungnya. Dengan suara yang bergetar, Kiai Surya Wisesa itu pun berkata, “Akulah pemenangnya. Aku akan menghujamkan keris ini di dadamu sebagai pertanda kemenanganku”
Kiai Surya Wisesa hampir tidak dapat mencapai tubuh Ki Sangga Geni yang terbaring diam. Tetapi masih terdengar Ki Sangga Geni itu berdesah perlahan sekali.
Namun langkah Kiai Surya Wisesa terhenti. Ia melihat Ki Margawasana berjongkok di sebelah tubuh Ki Sangga Geni.
“Apa yang akan kau lakukan, Kiai Surya Wisesa?“ bertanya Ki Margawasana.
“Aku akan membunuhnya. Dalam perang tanding, seorang diantara kami harus mati untuk menandai kemenangan bagi lawannya.
“Kau tidak perlu membunuhnya, Nafasnya sudah berada di ujung hidungnya. Biarlah kedua orang muridnya membawa tubuhnya meninggalkan arena ini”
“Aku harus membunuhnya. Akulah yang menang dalam perang tanding ini”
“Aku tahu. Kaulah pemenangnya. Berteriaklah kepada orang-orang Ngadireja bahwa kau telah memenangkan perang tanding ini. Tetapi kau tidak perlu menusuk tubuh ini dengan kerismu”
“Minggirlah Ki Margawasana agar aku tidak membunuhmu juga”
“Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa, Kiai Surya Wisesa.”
“Aku hanya akan membawa tubuh yang sudah hampir hangus ini pergi dari arena. Bukankah dengan demikian tidak akan merubah pendapat orang Ngadireja bahwa kau telah memenangkan perang tanding ini? Bahwa Ki Sangga Geni yang mempunyai kekuatan iblis itu telah kau kalahkan dengan kekuatan iblis pula? Itu adalah ciri dari kuasa iblis yang mengadu domba diantara mereka yang mengabdi kepadanya. Kau dan Ki Sangga Geni”
“Persetan dengan sesorahmu. Pergi atau aku akan membunuhmu disini”
“Kau sudah terlalu lemah Kiai Surya Wisesa. Seperti yang kau katakan tentang Ki Sangga Geni setelah membunuh muridmu. Bahwa dengan menutup hidungmu aku dapat membunuhmu”
”Tidak. Kau tidak akan dapat membunuhku, Tetapi akulah, orang yang tidak ada duanya inilah yang akan membunuhmu. Aku adalah orang yang memiliki ilmu tertinggi di atas bumi kita. Bahkan semua Senapati di Mataram tidak akan mampu mengalahkan aku”
“Aku tahu Kiai Surya Wisesa. Aku akui itu. Tetapi ijinkan kedua murid Ki Sangga Geni itu membawanya pergi”
“Tidak. Aku akan membunuhnya dan membiarkan tubuhnya terbaring ditempat itu. Biarlah burung-burung pemakan bangkai mencabik-cabik tubuhnya sehingga tinggal tulang-tulangnya”
Ki Margawasana tidak memperhatikan lagi kata-kata Kiai Surya Wisesa. Ia pun segera memberi isyarat kepada kedua orang murid Ki Sangga Geni untuk mendekat.
Namun demikian kedua orang murid Ki Sangga Geni itu berjongkok disamping tubuh guru mereka, Kiai Surya Wisesa itu pun berteriak, “Pergi. Pergi. Atau aku akan membantai kalian bertiga seperti aku akan mengoyak tubuh Sangga Geni”
Orang-orang yang berdiri di seputar arena itu menjadi berdebar-debar. Kemenangan Kiai Surya Wisesa membuat mereka menjadi sangat cemas. Meskipun Kiai Surya Wisesa sudah berjanji untuk tidak berbuat sebagaimana dilakukan oleh Kiai Pentog, namun mereka masih saja tetap curiga bahwa akhirnya mereka akan mengalami nasib yang sama sebagaimana masa Kiai Pentog berkuasa di daerah Ngadireja dan sekitarnya.
Dalam ketegangan itu, orang-orang yang berada di sekitar arena perang tanding itu melihat Kiai Surya Wisesa selangkah demi selangkah maju mendekati ketiga orang yang berada di sekitar Ki Sangga Geni.
Tetapi arena perang tanding dan sekitarnya itu bagaikan terguncang kembali ketika tiba-tiba bertiup angin pusaran. Angin pusaran itu seakan-akan tumbuh dari tubuh Ki Margawasana yang mulai menggerakkan tangannya.
Kiai Surya Wisesa pun terhenti. Angin pusaran itu semakin lama menjadi semakin besar dan semakin kencang.
Debu pun kemudian berhamburan. Daun-daun yang gugur ketika ranting-rantingnya berpatahan pada saat Kiai Surya Wisesa bertempur melawan Ki Sangga Geni pun berterbangan. Demikian pula dahan yang berpatahan. Bahkan gerumbul-gerumbul perdu pun telah tercerabut seakar-akarnya.
Rasa-rasanya tubuh Ki Sangga Geni serta ketiga orang yang berada di sekitarnya itu pun telah ditelan oleh angin pusaran yang keras. Sementara itu Kiai Surya Wisesa tidak lagi dapat mendekat. Setiap ia melangkah maju, maka tubuhnya telah terdorong surut oleh pusaran angin yang kencang itu.
Angin pusaran itu semakin lama semakin melebar, sehingga akhirnya meliputi daerah yang terhitung luas. Bahkan Kiai Surya Wisesa sendiri pun bagaikan ditelan oleh angin prahara itu.
Kiai Surya Wisesa tidak dapat menghanyutkan angin pusaran itu dengan ilmu pamungkasnya. Tubuhnya sudah menjadi terlalu lemah, sementara bagian dalam tubuhnya telah terluka cukup parah, sehingga darah meleleh di sela-sela bibirnya.
Jika Kiai Surya Wisesa itu memaksa diri untuk menghentakkan ilmu pamungkasnya, maka keadaan tentu akan menjadi semakin buruk. Bahkan mungkin ia akan dapat menjadi pingsan.
Namun akhirnya angin pusaran itu semakin lama menjadi semakin mereda. Debu serta dahan-dahan dan dedaunan yang terangkat pun telah melayang turun. Pohon-pohon perdu yang tercerabut serta berterbangan mulai berjatuhan.
Ketika sejenak kemudian angin pusaran itu sudah mereda dan bahkan debu pun telah mengendap, Kiai Surya Wisesa pun berdiri sambil mengusap matanya yang pedih.
Namun dalam pada itu, Ki Margawasana, kedua orang murid Ki Sangga Geni serta tubuh Ki Sangga Geni yang pingsan itu sudah tidak ada di tempatnya.
Ki Surya Wisesa lah yang kemudian melihat dikejauhan, dua orang murid Ki Sangga Geni yang mengusung tubuh gurunya, serta Ki Margawasana, berjalan cepat-cepat meninggalkan arena itu.
“Licik kau pengecut” teriak Kiai Surya Wisesa, “ingat. Pada suatu saat aku akan menyusulmu dan membunuhmu sebagaimana aku membunuh kecoa”
Meskipun Ki Margawasana masih mendengar teriakan itu, tetapi ia tidak berpaling. Kepada kedua orang murid Ki Sangga Geni, Ki Margawasana itu pun berkata, “Jangan hiraukan. Selamatkan gurumu. Mudah-mudahan lukanya masih sempat diobati”
Mereka pun berjalan semakin cepat. Semakin lama menjadi semakin jauh. Sementara itu, karena keadaan tubuhnya, maka Kiai Surya Wisesa tidak mungkin dapat menyusul mereka.
Ki Margawasana dan kedua orang murid Ki Sangga Geni telah membawanya ke tempat yang sepi. Mereka berhenti di dekat sebuah sendang yang agaknya tidak pernah dikunjungi orang. Beberapa batang pohon raksasa tumbuh disekitar sendang yang airnya melimpah itu. Bahkan agaknya air dari sendang itu telah dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Meskipun sendang itu sendiri tidak pernah dikunjungi, namun para petani telah membuat parit yang menampung air yang melimpah dari sendang itu.
Tubuh Ki Sangga Geni pun kemudian telah dibaringkan diatas rerumputan kering di tepi sendang itu.
Beberapa titik air sendang yang bening itu telah diteteskan di mulut Ki Sangga Geni.
Kemudian sebutir reramuan obat yang dibawa oleh Ki Margawasana telah dimasukkan kedalam mulut Ki Sangga Geni. Beberapa saat kemudian, Ki Sangga Geni pun mulai menjadi sadar. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Yang mula-mula dilihatnya adalah kedua orang muridnya.
“Aku sekarang berada dimana?“ bertanya Ki Sangga Geni dengan suara yang lemah.
“Kami berusaha menjauhkan guru dari arena. Kami belum tahu, dimana kami sekarang berada”
Ki Sangga Geni pun kemudian mulai mengingat-ingat apa yang telah terjadi.
Tiba-tiba saja Ki Sangga Geni itu pun berusaha untuk bangkit. Tetapi tulang-tulangnya terasa sakit dimana-mana. Sendi-sendinya seakan-akan telah terlepas yang satu dengan lainnya. Karena itu, maka Ki Sangga Geni telah terbaring lagi sambil berdesah menahan sakit.
“Berbaring sajalah Ki Sangga Geni“ terdengar suara Ki Margawasana.
Ki Sangga Geni mengerutkan dahinya. Dengan suara yang lemah dan bergetar ia pun berdesis, “Kau Ki Margawasana?“
“Ya”
“Apakah kau yang telah berusaha menyelamatkan nyawaku?“
“Daya tahanmu terlalu kuat Ki Sangga Geni. Aku tidak menyelamatkan nyawamu. Aku hanya mengantar murid-muridmu yang membawamu meninggalkan arena pertarungan”
“Kenapa kau tidak membiarkan aku mati di arena perang tanding itu?“
“Aku tidak dapat melihat Kiai Surya Wisesa menusuk dada seorang yang sedang pingsan. Ketika kau membenturkan ilmumu melawan ilmu puncak Kiai Surya Wisesa kau menjadi pingsan. Sementara itu meskipun keadaan Kiai Surya Wisesa juga parah, tetapi ia sempat bangkit berdiri dan tertatih-tatih mendekati tubuhmu yang pingsan. Ia mencabut kerisnya dan siap menghunjamkan kerisnya ke dadamu. Nah, pada saat itulah aku dan murid-muridmu membawa pergi. Kiai Surya Wisesa yang lemah itu tidak akan dapat mengejar kita Setelah kita sampai ke tempat ini, maka kita berhenti untuk beristirahat”
“Kau selamatkan aku agar di ujung bulan ini kita dapat berperang tanding?”
“Waktu aku dan murid-muridmu membawamu pergi, aku sama sekali tidak memikirkan kemungkinan itu. Kita juga tidak tahu, apakah dalam waktu sebulan kurang ini, kau akan dapat pulih kembali”
“Kalau aku belum pulih kembali dalam waktu sebulan kurang sedikit, bunuh saja aku”
“Kau kira aku dapat membunuh orang yang tidak berdaya? Aku dan kedua muridmu membawamu pergi dari arena karena aku tidak mau melihat Kiai Surya Wisesa itu membunuhmu pada saat kau tidak berdaya. Persoalannya akan berbeda jika kau mati pada saat kau dan Kiai Surya Wisesa membenturkan kekuatan Aji Pamungkas. Jika saat itu kau mati, maka kau benar-benar mati dalam perang tanding. Tetapi kau tidak mati. Karena itu dalam keadaan tidak berdaya aku agak berkeberatan jika Kiai Surya Wisesa menusuk dadamu di arah jantung”
Ki Sangga Geni terdiam. Terasa dadanya nyeri. Namun obat yang telah diletakkan di mulutnya serta hanyut oleh titik-titik air yang diteteskan disela-sela bibirnya, membuat perasaan sakit pada tubuhnya itu berkurang.
“Kau akan membawa aku kemana, Ki Margawasana?“ bertanya Ki Sangga Geni, “kau akan membawaku ke kaki Gunung Sumbing atau ke bukit kecilmu disebelah padukuhan Gebang”
“Aku akan membawamu ke Gebang. Aku akan mencoba merawatmu. Mungkin kau masih dapat sembuh”
Ki Sangga Geni menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab.
Untuk beberapa lama, mereka beristirahat. Kemudian Ki Margawasana itu pun telah mengajak kedua orang murid Ki Sangga Geni untuk membawa guru menempuh perjalanan ke Gebang.
“Perjalanan jauh. Bukankah lebih dekat jika kau bawa aku kembali ke kaki Gunung Sumbing. Bahkan perjalanan ke Gebang itu akan melewati lembah disekitar Gunung Sumbing”
“Tidak, Ki Sangga Geni. Aku ingin kau berada di Gebang. Aku sendiri yang akan merawat dan mengobatimu agar kau dapat sembuh pada waktunya”
Ki Sangga Geni itu menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak ingin mengelak. Ki Margawasana telah membawanya keluar dari arena perang tanding untuk memasuki perang tanding yang lain di akhir bulan.
Tetapi Ki Sangga Geni itu sempat juga merenungi pertarungan yang terjadi di Ngadireja. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ternyata masih ada yang dapat melampaui tingkat ilmunya yang dianggapnya sudah sempurna.
“Mungkin yang terjadi hanyalah kebetulan atau bahkan kecelakaan” berkata Ki Sangga Geni didalam hatinya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Margawasana sebelum ia berangkat ke Ngadireja bahwa Kiai Surya Wisesa sempat mempelajari ilmunya serta mencari kelemahan-kelemahannya.?
“Ternyata Ki Margawasana benar. Agaknya Kiai Surya Wisesa berhasil melihat kelemahan-kelemahanku serta mempelajari bagaimana caranya ia dapat menembus kelemahan-kelemahanku itu”
Demikianlah, maka mereka pun telah menempuh perjalanan yang panjang menuju ke Gebang. Meskipun mereka melewati lembah di kaki Gunung Sumbing, tetapi mereka tidak singgah. Dengan bantuan reramuan obat yang diberikan oleh Ki Margawasana, Ki Sangga Geni berusaha untuk berjalan sendiri meskipun bergantian kedua orang muridnya masih harus membantunya.
Perjalanan yang panjang itu ternyata memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam keadaan terluka, Ki Sangga Geni harus menempuh perjalanan tiga hari. Di malam hari mereka bermalam di padang perdu atau pategalan. Sementara di siang hari mereka menempuh perjalanan meskipun mereka harus sering beristirahat.
Lewat tiga hari tiga malam, maka mereka pun telah sampai di Gebang. Mereka langsung menuju ke rumah Ki Margawasana yang berada di bukit kecil.
Ketika mereka sampai di bukit kecil itu, rasa-rasanya Ki Sangga Geni telah sampai ke sebuah istana yang akan memberikan tempat yang sangat nyaman baginya.
“Beristirahatlah sebaik-baiknya Ki Sangga Geni” berkata Ki Margawasana, “untunglah bahwa daya tahanmu sangat kuat, sehingga kau mampu menyelesaikan perjalanan yang panjang ini. Kau dapat bertahan sampai ke bukit kecil yang sepi ini”
“Kau telah membantuku dengan reramuan obat-obatanmu, Ki Margawasana”
“Nah, kau harus beristirahat cukup agar kau dapat segera pulih kembali”
Ki Sangga Geni hanya dapat menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menolak ketika Ki Margawasana minta kepadanya agar ia banyak berbaring di pembaringan.
Dengan demikian, maka Ki Sangga Geni mempunyai banyak waktu untuk merenung. Berbagai macam persoalan hilir murid di kepalanya. Sebenarnyalah bahwa ia merasa heran, kenapa Ki Margawasana bersusah payah pergi ke Ngadireja. Mungkin Ki Margawasana ingin melihat, sejauh manakah tingkat ilmunya sekarang, setelah ia minta waktu setahun untuk menuntaskan laku agar ia dapat menguasai ilmunya sampai tuntas.
Tetapi ketika ia mengalami kekalahan dari Kiai Surya Wisesa, kenapa Ki Margawasana masih berusaha untuk menolongnya.
“Agaknya Ki Margawasana memang seorang yang sangat sombong. Ia pun ingin menunjukkan kepadaku, bahwa ia lebih baik dari aku. Ia ingin agar perang tanding beberapa pekan lagi itu dapat berlangsung agar ia dapat menunjukkan, bahwa aku tetap saja tidak dapat mengalahkannya”
Tiba-tiba saja Ki Sangga Geni menggeram. Katanya kepada dirinya sendiri, “Tetapi Ki Margawasana akan menyesal. Aku akan melumatkannya. Atau Ki Margawasana itu harus berlutut dihadapanku, membungkuk sampai mencium tanah mohon ampun kepadaku”
Dalam pada itu, Ki Margawasana merawat Ki Sangga Geni dengan bersungguh-sungguh. Diberikannya reramuan obat terbaik yang dapat dibuatnya. Sehingga dengan demikian, dari hari ke hari, keadaan Ki Sangga Geni menjadi semakin baik. Bahkan tenaganya pun telah menjadi hampir pulih kembali.
Ketika diam-diam ia mencoba kemampuannya di sanggar terbuka Ki Margawasana, maka ketangkasan serta ketrampilan-nya pun hampir pulih kembali.
Meskipun demikian, jika ia memaksa diri dengan gerakan-gerakan yang berat, dadanya masih terasa nyeri.
Namun dari hari ke hari, keadaannya menjadi semakin baik.
Tetapi pada saat Ki Sangga Geni merasa bahwa ia telah sembuh kembali, serta segala-galanya telah pulih sebelum hari yang menggenapi satu tahun dari kekalahan Ki Sangga Geni di padepokan Ki Udyana, Kiai Surya Wisesa telah datang ke bukit kecil disebelah padukuhan Gebang itu.
Kiai Surya Wisesa langsung memasuki halaman rumah kecil Ki Margawasana dengan memanggil namanya.
“Ki Margawasana. Ini aku, Kiai Surya Wisesa”
Suaranya telah mengejutkan sisi rumah kecil itu. Ki Margawasana, Ki Sangga Geni serta kedua muridnya pun segera keluar dari rumah kecil itu. Mereka melihat Kiai Surya Wisesa berdiri di halaman dengan tangan bersilang didadanya.
“Kiai Surya Wisesa” desis Ki Margawasana;
“Ya” sahut Ki Surya Wisesa, “Kau tentu sudah menduga, bahwa pada suatu hari aku tentu datang kepadamu”
Ki Margawasana mengangguk-angguk. Katanya, “Ya. Aku memang sudah menduga, bahwa kau tentu akan menyusul aku kemari, karena aku telah membawa Ki Sangga Geni dari arena perang tanding pada waktu itu”
“Kiai Surya Wisesa” berkata Ki Sangga Geni, “jika kau datang untuk menyusul aku, maka sekarang aku sudah siap untuk bertarung lagi. Aku juga sudah sembuh sebagaimana kau yang nampaknya juga sudah sembuh”
“Aku memang sudah sembuh, Ki Sangga Geni. Tetapi aku tidak datang untuk mencarimu. Semua orang di Ngadireja dan sekitarnya, sudah tahu, bahwa aku telah memenangkan perang tanding melawanmu. Berita tentang kemenanganku itu tentu sudah menjalar kemana-mana. Semua gegedug dan orang-orang berilmu tinggi sudah mengerti, bahwa aku telah mengalahkan orang yang membunuh Pentog”
“Tidak“ Ki Sangga Geni itu menyahut dengan suara lantang, “kita akan membuktikannya sekali lagi. Siapakah diantara kita yang terbaik di bumi ini”
“Pada saatnya kita akan membuktikannya. Tetapi sekarang aku ingin menunjukkan kepada orang-orang di Ngadireja, bahwa orang yang telah menyelamatkan Ki Sangga Geni dengan angin pusarannya itu bukan orang yang terbaik. Aku akan menantangnya dan membunuhnya dihadapan orang-orang Ngadireja. Selama ini mereka mendapat kesan, seolah-olah orang yang bermain-main dengan angin pusaran itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, sehingga melampaui ilmuku”
“Ki Surya Wisesa. kenapa kau demikian bernafsu untuk disebut yang terbaik? Silahkan. Apa pun yang akan kau lakukan aku tidak akan pernah menghalanginya. Kalau kau tantang aku untuk berperang tanding di Ngadireja sekedar untuk menunjukkan bahwa salah seorang diantara kita adalah orang yang terbaik, lebih baik aku menolaknya. Jika karena aku tidak datang ke arena, kemudian orang-orang Ngadireja menganggap bahwa aku takut terhadap orang yang memiliki ilmu tertinggi di negeri ini, dan itu dapat memberi kepuasan kepadamu, silahkan saja. Aku sama sekali tidak berkeberatan”
“Pengecut” geram Kiai Surya Wisesa, “Kenapa kau tidak berani tampil di perang tanding itu? Apakah kau takut mati? Seorang yang menyatakan dirinya berilmu tinggi tentu akan berani menghadapi tantangan dari siapa pun juga”
“Aku bukan seorang yang menyatakan diriku berilmu tinggi”
Kata-kata itu agaknya telah menggelitik perasaan Ki Sangga Geni sehingga ia pun berkata, “Kenapa tidak kau tantang aku saja, Kiai Surya Wisesa. kalau kau anggap Ki Margawasana sebagai seorang pengecut, maka tantang aku. Aku akan hadir di arena perang tanding itu lagi. Aku akan membuktikan, bahwa kemenanganmu beberapa saat yang lalu, adalah satu kebetulan. Hal itu merupakan satu kecelakaan bagiku karena aku menjadi lengah”
“Omong kosong. Kau sudah tidak berharga lagi bagiku. Aku hanya ingin menghancurkan nama Ki Margawasana karena ia telah menimbulkan kesan yang keliru di Ngadireja. Ada diantara mereka yang menganggap bahwa permainan angin pusaranmu itu mampu melampaui ilmuku karena aku tidak dapat membunuhmu waktu itu. Mereka, yang mengagumimu itu tidak mau tahu, bahwa pada saat itu aku sudah terluka, sehingga aku tidak akan dapat berbuat banyak terhadapmu. Agaknya kau berani melakukan apa yang kau lakukan pada waktu itu juga karena kau tahu, bahwa aku tidak akan dapat mengejarmu”
“Katakan kepada mereka, bahwa pada waktu itu aku telah berlindung dibalik angin pusaran itu. Kemudian aku pun telah melarikan diri”
“Tidak“ Ki Sangga Geni hampir berteriak, “kita bukan orang-orang licik seperti itu. Kalau Kiai Surya Wisesa menolak melawan aku lagi, maka Ki Margawasana harus datang ke Ngadireja. Persoalan diantara kita akan kita selesaikan kemudian. Persoalan diantara kita tidak menyangkut pengakuan orang banyak sebagaimana orang-orang Ngadireja itu”
“Tidak ada. gunanya, Ki Sangga Geni. Aku tidak ingin memamerkan ilmuku dihadapan orang banyak”
“Bukan soal memamerkan ilmu. Tetapi soal harga diri Ki Margawasana. Bukankah Ki Margawasana hanya melayani Kiai Surya Wisesa?”
“Aku tidak akan pergi ke Ngadireja”
“Inilah yang aneh pada orang-orang sepertimu. Orang-orang yang tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Orang yang tidak tahu menjunjung nama dan martabatnya” gigi Ki Sangga Geni lah yang justru menjadi gemeretak menahan gejolak di dadanya. Lalu katanya dengan lantang, “Kiai Surya Wisesa. Apakah kau tiba-tiba saja menjadi ketakutan melihat kesiapanku sekarang ini sehingga kau menolak untuk menantangku lagi. Bagaimana pendapatmu jika akulah yang menantangmu untuk berperang tanding di Ngadireja. Aku juga ingin mengatakan kepada orang-orang Ngadireja bahwa guru orang yang menyebut dirinya Pentog itu pun tidak sanggup mengalahkan aku”
-oo0dw0oo-
bersambung ke jilid 19
Karya : SH Mintardja
Sumber DJVU http ://gagakseta.wordpress.com/
Convert by : DewiKZ
Editor : Dino
Final Edit & Ebook : Dewi KZ
http://kangzusi.com/ http://dewi-kz.info/
http://ebook-dewikz.com/ http://kang-zusi.info
edit ulang untuk blog ini oleh Arema







Tinggalkan komentar